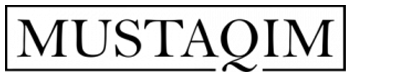Mustaqim.NET – Kisah yang akan kami sajikan ini merupakan ringkasan dari buku yang berjudul Aminah: Kisah Cinta Ibunda Rasulullah, buah karya dari abdul Mun’im Muhammad Umar.
Masa Kecil Aminah
Sayidah Aminah tumbuh sebagai anak yang selalu menarik perhatian orang-orang Mekkah. Saat ia bermain dengan teman-teman sebayanya, banyak orang kerap mengerumuninya. Bukan karena ia paham maksudnya, melainkan karena mereka ingin menikmati tutur katanya yang manis, jujur, dan merdu. Sayidah Aminah juga ikut menjalani keseharian anak-anak Mekkah: bermain di sekitar Ka’bah, duduk-duduk di dekat sumur Zamzam, menyaksikan orang-orang kuat berebut air.
Pesona Aminah digambarkan bukan hanya karena kecantikannya (fisik yang segar, postur ramping, mata lebar, rambut panjang), tetapi juga karena kepribadiannya: cekatan, lembut, tangkas, berwawasan, dan cerdas. Ia adalah anak yatim yang diasuh pamannya, Wuhaib ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah, kepala Bani Zuhrah; marga terhormat Quraisy yang rumah-rumahnya dekat Ka’bah, menandakan kedudukan sosial yang tinggi. Wuhaib sangat menyayangi Aminah karena melihat bayang-bayang saudara sekaligus ayah Aminah (Wahb) dalam diri Aminah. Kasih sayang itu juga didukung istri Wuhaib dan anak-anaknya, sehingga Aminah tumbuh nyaman tanpa merasa kekurangan perhatian.
Tokoh yang paling dekat dengan Aminah adalah Halah, putri Wuhaib. Mereka tumbuh seperti saudari, namun ketika memasuki usia remaja (Halah 14 tahun, Aminah mendekati 12 tahun), tradisi keluarga terhormat membuat mereka lebih jarang terlihat di luar rumah. Setelah Halah bertunangan dan menikah dengan Abdul Muththalib ibn Hasyim, ia pindah rumah tetapi hubungan mereka tetap erat; saling berkunjung untuk melepas rindu. Dalam pertemuan-pertemuan itu, mereka membicarakan “berita Mekkah” yang tak pernah habis karena Mekkah adalah pusat persinggahan kafilah, tempat Ka’bah, dan pusat pasar serta prestise sosial.
Pada akhirnya, Halah mulai memperhatikan Aminah dengan pandangan yang “cermat” seolah menunggu sesuatu terungkap; Aminah pun merasa ada “rahasia hati” yang sulit disembunyikan dari Halah, tetapi keduanya masih menahannya dalam percakapan yang dialihkan ke topik keramaian Mekkah.
Rahasia Perjodohan
Aminah menjadi pujaan Mekkah karena kecantikan, etika, kecerdasan, dan kesederhanaannya, sementara Abdullah ibn Abdul Muththalib juga masyhur sebagai pemuda cerdas, dermawan, dan tampan. Halah binti Wuhaib yakin Aminah paling pantas untuk Abdullah. Ia menunggu saat suaminya, Abdul Muththalib, tidak lagi kalut, lalu memastikan bahwa sang suami memang berniat menikahkan Abdullah dan condong memilih Aminah. Pada malam hari, Halah mendatangi ayahnya, Wuhaib, untuk meminta agar pinangan-pinangan lain ditahan sampai niat Abdul Muththalib disampaikan secara resmi.
Wuhaib: “Menurutmu, siapakah yang pantas mendapatkan Aminah?”
Halah: “Tidak ada seorang pun, wahai Ayahku! Tidak seorang pun di antara mereka yang pantas mendapatkan Aminah. Aminah hanya pantas untuk seorang pemuda istimewa yang mengungguli dan mengalahkan mereka semua.”
Wuhaib: “Siapa dia, wahai Halah?”
Halah: “Abdullah ibn Abdul Muththalib, wahai Ayahku! Pemuda Quraisy yang paling tampan, paling suci, paling cerdas, yang terjauhkan dari cara hidup pemuda-pemuda Quraisy yang penuh kebusukan dan pemuasan birahi hawa nafsu. Dari wajahnya terpancar cahaya terang sebagaimana wajah Aminah. Tidakkah cahaya itu lebih pantas untuk cahaya ini, wahai Ayahku?”
Wuhaib: “Apakah engkau mengetahui, wahai Halah, bahwa Abdul Muththalib juga berkehendak menjodohkan anaknya, Abdullah? Dan apakah engkau yakin dia menghendaki Aminah?”
Halah: “Ya, wahai Ayahku. Suatu hari aku berbincang-bincang dengannya. Aku menanti kesempatan membicarakan hal ini kepadanya. Hingga hari ini, aku baru mengetahui niatnya untuk menikahkan Abdullah, setelah beban berat terasa hilang dari pundaknya. Kemudian, aku ajukan kepadanya gadis-gadis anak orang kaya Quraisy dan para pembesarnya selain Aminah. Abdul Muththalib menolak semuanya, berseru kepadaku dengan bangga, ‘Tidak, wahai Halah! Aku tidak ingin menjodohkan perempuan-perempuan tersebut dengan Abdullah!
Aku menginginkan untuknya seorang perempuan cantik, cerdas, suci, dan pintar. Aku menginginkan perempuan yang bisa mengatur dan menanggung beban hidup bersama suaminya. Saat suaminya bahagia, ia pun bahagia karenanya. Saat susah, ia pun susah karenanya. Mampu menjaganya saat ia tidak ada di rumah, dan bahagia saat ia kembali pulang, mampu mendorongnya menuju keagungan. Bersama-sama membangun sangkar yang tenang dan nyaman, tempat keduanya berkicau. Dan anak-anaknya pun turut berkicau dengan senandung manis dan suci.
Aku menginginkan perempuan dari Bani Abdi Manaf, wahai Halah! Keluarga terhormat kabilah Quraisy, dari tulang-tulang rusuk yang suci! Lupakah engkau akan pengaruh seorang perempuan terhadap laki-laki, wahai Halah? Perempuan yang baik, suci, dan saleh adalah sandaran sepanjang masa, dan kekuatan dalam menghadapi perjalanan waktu.’
Segera aku tahu saat itu Abdul Muththalib menghendaki Aminah, wahai Ayahku. Tidak ada di kalangan Quraisy, bahkan bangsa Arab seluruhnya, perempuan yang mempunyai sifat-sifat tersebut selain Aminah. Tidakkah engkau melihat, wahai Ayahku, bahwa Abdul Muththalib benar-benar menghendaki Aminah?”
Wuhaib: “Benar, wahai Halah, sifat-sifat tersebut hanya dimiliki oleh Aminah. Namun, apa sebenarnya yang menghalangi Abdul Muththalib? Mengapa sampai sekarang dia tidak mendatangiku dan memintanya kepadaku, atau mengutarakan maksudnya kepadaku?
Sedikit pun aku tidak menemukan adanya maksud ini di wajahnya, wahai Halah. Hari-hari ini aku hanya melihatnya sedang galau, seakan-akan mewaspadai bahaya yang akan menimpanya sewaktu-waktu.
Namun, apakah sebab itu kemudian dia tidak memikirkan kepentingan orang lain, sedangkan dia adalah orang dermawan, pemberani, dan bertakwa, yang mengimani takdir dan kekuatan Allah, dan segala sesuatu ada di tangan-Nya?”
Halah: “Memang pikiran itu sedang menguasai jiwanya, wahai Ayahku! Menjauhkannya dari segala hal. Dan aku tidak mengerti sebab kegalauan ini.
Dia bukan seorang pengutang yang selalu terbebani dan dikuasai oleh utang-utangnya, menjadi hamba para lintah darat yang menjerat lehernya dan hidup menderita dalam impitan utang.
Dia juga bukan orang miskin yang selalu memikirkan dunia dan bagaimana menjadi orang kaya. Dia telah dikaruniai keturunan seperti yang diinginkan; anak-anaknya pun banyak, dan dirinya merasa tenang dengan anugerah ini.
Namun aku melihat dia akan segera menemukan jalan keluar, wahai Ayahku. Cemas dan risau yang menguasainya akan segera hilang. Dan dia akan bergegas mendatangimu untuk meminta Aminah.”
Wuhaib: “Kapan hal itu, wahai Halah? Tidakkah Abdul Muththalib mengetahui tindakan para pembesar Quraisy yang tidak henti-hentinya meminang Aminah siang dan malam, terus mendesak kita—dengan dirinya sendiri atau melalui perantara sanak kerabat kita, sanak kerabat mereka, atau para pembesar Mekkah yang lain? Tidakkah Abdul Muththalib khawatir seandainya aku merestui permintaan mereka?
Apakah dia hendak menjadikan masa depan Aminah menggantung dalam misteri waktu? Sedangkan sudah saatnya Aminah membuka kehidupan baru, bahagia mengarungi hidup bersama suaminya, dan mencurahkan hidupnya untuk anaknya?”
Halah: “Sudah barang tentu, wahai Ayahku, Abdul Muththalib bertumpu pada tingginya nalar dan kecerdasanmu. Dia sudah mengetahui dengan yakin bahwa engkau dapat sampai ke lubuk hatinya dan memahami keinginannya, dan engkau tidak akan menerima tunangan para pemuda yang dibutakan oleh kemewahan dunia, terseret ke kesenangan hawa nafsu, dan hanyut dalam samudra kelalaian, senda gurau, serta kerusakan.
Aku pun yakin niat baik Abdul Muththalib telah engkau tangkap dengan jelas, wahai Ayahku. Tentunya engkau ingat bagaimana Abdul Muththalib mendekat dan bersimpati kepada Aminah, memberikan perhatian besar. Tidak ada bukti yang lebih jelas, kecuali hadiah yang dibawanya untuk Aminah dari negeri Yaman.
Tidakkah baju sutra murni yang penuh hiasan adalah hadiah yang biasanya diberikan kepada calon pengantin?
Sudah pasti dia menghendaki Aminah untuk putranya, Abdullah, wahai Ayahku. Tetapi dia masih menunggu hingga suasana hatinya tenang dan kebahagiaan kembali menyapanya. Hari-hari ini aku melihatnya sangat tertekan dan begitu galau, dan aku menduga badai kekalutan itu akan segera berakhir.
Maka bersabarlah, wahai Ayahku. Hari-hari berjalan cepat. Aminah masih belia, meski ia terus tumbuh dan tampak tinggi semampai melampaui usianya. Dan aku tidak merahasiakan kepadamu bahwa Abdullah pun memiliki rasa yang sama, hanya saja dia tidak seperti pemuda-pemuda lain yang selalu menuruti hawa nafsu dan suka melanggar keinginan orang tua.”
Wuhaib: “Wahai Halah, apakah menurutmu aku sebaiknya menolak semua pinangan para pemuda itu dan menunggu ketenangan hati Abdul Muththalib?”
Halah: “Benar, wahai Ayahku. Tidak ada keraguan tentang itu, setelah aku melihat dan mendengarnya langsung dari Abdul Muththalib.
Dan tidak ada kerugian sedikit pun bila kita menunggunya. Abdul Muththalib tidak akan mengubah pikirannya. Aminah telah menjadi milik Abdullah. Aku berdoa semoga Tuhan memberikan pertolongan-Nya, menjauhkan kita dari segala rintangan, dan menghilangkan kekalutan yang diderita Abdul Muththalib.”
Halah tetap menyimpan rahasia itu dari Aminah, namun ia memberi isyarat akan ada kabar baik esok hari.
Halah: “Besok ada kabar baik untukmu, wahai Aminah! Jangan lupa, ya. Awas kalau sampai terlambat.”
Kunjungan Abdul Muththalib ibn Hasyim
Menjelang tengah hari, panas Kota Mekkah seakan memancar dari gunung-gunungnya. Kebanyakan orang menghentikan aktivitas dan berlindung di rumah. Namun Abdul Muththalib ibn Hasyim justru berjalan menembus terik menuju rumah sahabatnya, Wuhaib ibn Zuhrah. Mereka berbincang hingga panas mulai mereda, lalu bersiap menuju tempat berkumpul di dekat Ka’bah bersama para pembesar Quraisy.
Wuhaib mengangkat tema musim haji: betapa jemaah bertahan di Arafah dalam terik, lalu singgah di Mina yang diapit dua gunung, dan tetap bertawaf serta sa’i di antara Shafa dan Marwah meski panas terasa menggigit. Abdul Muththalib tampak gelisah; pandangannya sesekali tertuju ke halaman rumah dan kepada Aminah, yang melayani keduanya dengan sigap tanpa menyerahkan tugas itu kepada pembantu.
Di sela percakapan, Wuhaib menyinggung jasa besar Abdul Muththalib karena Zamzam. Nama Zamzam seolah menyentakkan Abdul Muththalib dari lamunannya.
Wuhaib:
“Aku tidak mengerti apa yang akan dilakukan para jemaah haji di tengah terik matahari yang sangat panas, seandainya engkau, wahai Abdul Muththalib, tidak menemukan dan menggali sumur Zamzam, lalu mengeluarkan darinya air yang melimpah.”
Abdul Muththalib:
“Tuhan tidak melupakan hamba-hamba-Nya yang tulus, wahai Wuhaib. Dia melihat kebingungan, dahaga, dan penderitaan para hamba-Nya pada musim haji. Lalu Dia memberiku hidayah untuk menggali sumur Zamzam agar mereka dapat minum, agar beban mereka ringan, dan agar mereka mampu menjalankan ketaatan yang susah payah—menempuh padang pasir dan gunung-gunung terjal.
Karena itu mereka memacu unta-unta, bertalbiyah, dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Luhur dan Maha Besar. Mereka adalah hamba dan kekasih Allah, wahai Wuhaib. Allah berbelas kasih kepada mereka dan melimpahkan rahmat-Nya, dan Dia menjadikanku perantara rahmat-Nya bagi hamba-hamba-Nya. Kalau bukan karena petunjuk-Nya, kita tidak akan memperoleh kebajikan ini.”
Wuhaib (tersenyum):
“Semoga Allah merahmati mereka dan juga engkau, wahai Abdul Muththalib. Semoga Allah membalas jerih payahmu saat menyediakan air Zamzam yang menyegarkan seluruh jemaah haji. Dan semoga Allah membalas kesengsaraanmu ketika membuatkan mereka tempat air dari kulit sebagai wadah minum selama musim haji, yang mereka bawa ke mana pun mereka pergi. Sungguh itu pengorbanan besar; namun anugerah Allah lebih besar, dan rahmat-Nya sangat luas.”
Wuhaib (melanjutkan):
“Ingatkah engkau, wahai Abdul Muththalib, ketika orang-orang Quraisy menghalangimu menggali sumur Zamzam dan mengeluarkan airnya? Dan ingatkah engkau ketika mereka ingin ikut menikmati anugerah mulia ini bersamamu? Allah mengkhususkannya untukmu setelah engkau bersikeras dengan tekadmu hingga air Zamzam keluar jernih.”
Ketika Aminah menyuguhkan kurma dan air Zamzam yang didinginkan, Abdul Muththalib memuji rasa suguhan itu—bukan semata karena bahan, melainkan karena tangan Aminah yang menyajikannya. Ucapan itu membuat pembicaraan berbelok ke hal yang lebih dalam: Aminah telah dewasa dan pinangan para pembesar Quraisy terus berdatangan. Abdul Muththalib meminta Wuhaib bersabar beberapa hari, karena ia berharap Aminah kelak menjadi bagian keluarga Bani Abdul Muththalib.
Abdul Muththalib (setelah disuguhi):
“Alangkah lezatnya kurma ini, dan alangkah manisnya air ini.”
Wuhaib:
“Ini kurma negeri kita—tidak berubah, wahai Abdul Muththalib—dan kita membelinya. Engkau pun memakannya sebagaimana kami. Dan air itu air Zamzam, hanya saja didinginkan; tidak ada yang baru. Lalu apa maksud pujian ini?”
Abdul Muththalib:
“Benar, ini kurma negeri kita, dan ini air Zamzam. Tetapi tangan Aminah yang menyuguhkannya, wahai sahabatku.
Setiap yang disuguhkan oleh Aminah terasa lebih lezat dan lebih nikmat. Aku tidak memakan makanan yang ia suguhkan dan meminum minuman yang ia berikan, kecuali aku merasakan semuanya tidak seperti biasanya.”
Abdul Muththalib (memecah hening):
“Aminah telah beranjak dewasa, wahai Wuhaib.”
Wuhaib (tanggap):
“Dia adalah putriku, wahai Abdul Muththalib, dan akulah walinya. Maka utarakanlah maksudmu. Wuhaib tidak akan menghalangimu—begitu pula orang lain.”
Abdul Muththalib:
“Sabar, wahai Wuhaib. Aku telah mendengar kabar tentang para utusan yang datang kepadamu tiap pagi dan sore. Mereka menawarkan apa pun agar dapat meminang Aminah.”
Abdul Muththalib (melanjutkan):
“Aminah memang layak diperebutkan para pembesar bangsa Arab. Pada masa ini, sulit menemukan perempuan yang menyamai Aminah. Maka bersabarlah sejenak, wahai sahabatku. Semoga saja ia menjadi milik Bani Abdul Muththalib. Hanya sebentar, beberapa hari ini saja, wahai Wuhaib. Setelah itu semuanya akan jelas.”
Namun ternyata kegelisahan Abdul Muththalib bukan hanya soal perjodohan. Ia masih dibebani nazar lama: bila Allah menganugerahinya sepuluh anak laki-laki, ia akan menyembelih satu di antaranya sebagai kurban. Kini jumlah anaknya telah genap, dan ia merasa waktunya menepati nazar. Wuhaib menolak gagasan itu—menganggapnya membuka pintu fitnah dan kekejaman—tetapi Abdul Muththalib tetap menyerahkan urusan pada kehendak Tuhan.
Wuhaib (setelah memahami kegelisahan lain):
“Masihkah engkau memikirkan hal itu, wahai Abdul Muththalib?”
Abdul Muththalib (cepat dan serius):
“Benar, wahai sahabatku. Aku telah bernazar, dan aku akan memenuhinya. Aku akan menyembelih salah satu putraku sebagai kurban kepada Tuhanku. Apakah engkau mengira nazarku hanya canda?
Situasi saat itu sangat sulit dan menegangkan. Ingatkah engkau hari itu, wahai Wuhaib? Ketika orang-orang Quraisy mengerumuniku saat aku mengangkat cangkul dan memukulkannya ke tanah untuk mencari sumber Zamzam—sebagaimana diperintahkan Tuhanku dan diisyaratkan oleh suara yang berbisik kepadaku.
Mereka memusuhiku. Aku tidak menzalimi mereka dan tidak mencelakai seorang pun. Saat itu hanya putraku, al-Harits, seorang yang berdiri di belakangku. Hatiku hampir hancur.
Aku hanya memiliki satu putra, sedangkan orang-orang Quraisy di sekelilingku memiliki banyak anak laki-laki yang ikut memusuhiku.”
Abdul Muththalib (setelah tenang):
“Saat itu aku benar-benar membutuhkan banyak anak laki-laki, wahai Wuhaib—sebagaimana yang dibanggakan Quraisy. Aku bernazar: jika Allah menganugerahiku sepuluh anak laki-laki, aku akan menyembelih satu di antaranya sebagai kurban. Sekarang Allah telah mengabulkan doaku. Apakah aku kemudian kikir mengorbankan satu putraku demi Tuhanku?
Apakah itu terbilang banyak, wahai sahabatku, bila aku mempersembahkan satu putra kepada Tuhan Yang Maha Memberi dan Maha Menolak, Yang Maha Merendahkan dan Maha Memuliakan?
Orang-orang melupakan nazar itu, wahai Wuhaib, tetapi Abdul Muththalib mengingatnya siang dan malam. Mereka meminum air Zamzam, namun lupa bahwa ‘harga’ air itu adalah sepotong hati dan darah daging Abdul Muththalib. Mereka pun tidak tahu bahwa masa pemenuhan nazar telah tiba.”
Wuhaib:
“Namun mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mengorbankan manusia adalah sesuatu yang mengherankan, wahai Abdul Muththalib—sesuatu yang tidak diakui tradisi orang Arab dan aturannya.
Orang Arab, wahai Abdul Muththalib, lebih lembut dan malu untuk melakukan apa yang dilakukan sebagian bangsa asing yang keras hati: menyembelih manusia sebagai kurban.
Itu tindakan bengis, wahai Abdul Muththalib, yang akan membangkitkan kemarahan orang Arab. Maka pertimbangkanlah sekali lagi. Jangan engkau membuka pintu fitnah ini dan membuat aturan baru yang kejam, sedangkan engkau adalah figur baik yang menghilangkan dahaga dan menyingkirkan lapar.”
Abdul Muththalib (tenang):
“Kehendak Tuhan, wahai sahabatku. Tiada yang dapat menolak kehendak-Nya. Abdul Muththalib maupun yang lain tidak dapat menghalanginya atau menunda pelaksanaan kehendak-Nya.”
Aminah mendengar semuanya dari dekat. Hatinya sesak membayangkan salah satu putra Abdul Muththalib benar-benar akan dikurbankan. Ia berbisik-bisik dalam cemas, berharap nazar itu dapat ditebus dengan harta atau unta.
Aminah (berbisik dalam hati):
“Tidakkah nazar ini dapat ditebus? Tidak mampukah Abdul Muththalib menggantinya dengan beberapa ekor unta atau sebagian hartanya? Bukankah nazar dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Lalu, keuntungan apa yang ‘dinikmati’ Tuhan dari penyembelihan seorang manusia?”
Aminah (bertanya pada diri sendiri):
“Siapakah anak malang itu yang akan disembelih oleh ayahnya? Bagaimana Abdul Muththalib memilih kurbannya?”
Ketika bayang-bayang gunung mulai memanjang dan orang-orang kembali keluar dari rumah, Abdul Muththalib dan Wuhaib beranjak menuju Ka’bah. Aminah tetap terdiam, dihantui satu pertanyaan: siapakah anak yang akan dipilih?
Kemelut Batin
Malam itu terasa panjang. Rumah Abdul Muththalib membludak oleh orang-orang Quraisy dan non-Quraisy. Mereka datang untuk satu tujuan: mencegah nazar yang akan ia tunaikan—nazar yang, bagi banyak orang, akan melahirkan tradisi baru yang mengerikan dan menjerumuskan seorang pemuda ke ambang kematian.
Orang-orang membicarakan akibat nazar itu dengan suara pilu dan marah. Namun Abdul Muththalib mendengarkan tanpa banyak menanggapi. Ia hanya mengulang satu kalimat yang membuat suasana makin tegang:
“Aku telah bernazar, dan harus dilaksanakan.”
Di sekelilingnya, putra-putranya berdiri tenang. Tidak tampak gentar di wajah mereka, seolah mereka telah menerima tekad ayahnya sebagai keputusan yang tak bisa diganggu gugat. Bahkan, mereka menyatakan kesiapan dengan lantang:
“Wahai ayahku! Laksanakan kehendakmu dan gapailah rida Tuhanmu. Jangan engkau langgar janji yang telah engkau ucapkan, sedangkan engkau adalah orang yang bertakwa dan menepati janji. Jiwaku ada di bawah kehendakmu, dan kepalaku ada di tanganmu.”
Keberanian itu membuat banyak orang tercengang. Tetapi di sisi lain, istri-istri Abdul Muththalib menangis; para ibu memeluk kecemasan, takut jika undian kelak jatuh pada putra mereka. Putri-putri rumah itu pun ikut memohon, berharap nazar dapat ditebus dengan harta atau unta. Namun jawaban Abdul Muththalib tetap sama, dingin dan teguh:
“Aku telah bernazar, dan harus dilaksanakan.”
Menjelang fajar, Kota Mekkah tidak tidur. Di rumah-rumah, orang-orang bergolak—para perempuan mencela para suami karena dianggap gagal menghentikan rencana itu. Ketegangan meledak dalam benak sebagian laki-laki; bayangan seorang ayah menghunus pisau ke leher anaknya membuat mereka tersentak. Dari balik pintu, ada yang berteriak keras menolak:
“Tidak akan aku biarkan Abdul Muththalib melaksanakan nazarnya. Tidak akan aku biarkan dia menyembelih anaknya. Darah seseorang tidak boleh mengalir hanya karena kesalahan ucap. Aku tidak peduli! Biarkan Tuhan berbuat sesuka hati-Nya.”
Di sisi lain, para gadis Mekkah yang menaruh harap pada Abdullah menangisi kemungkinan terburuk: semoga undian tidak memilih pemuda yang mereka dambakan. Sementara itu, Aminah melewati malam dengan doa yang tak putus, berharap Allah membuka jalan keluar, sebagaimana kisah Ibrahim dan Ismail—sebuah ujian yang pada akhirnya diganti dengan tebusan.
Pagi datang. Orang-orang berbondong-bondong keluar, termasuk pendatang dari luar Mekkah yang ingin menyaksikan peristiwa tragis itu. Matahari merangkak naik. Abdul Muththalib keluar dari rumahnya membawa pisau besar yang berkilat. Putra-putranya mengiringi; para ibu dan bibi mengikuti dengan tangis dan ratap; orang-orang mengekor dalam gelombang kerumunan.
Mereka tiba di depan Ka’bah, bertawaf, lalu berhenti di hadapan Hubal. Amarah, takut, dan jijik bercampur jadi satu di mata massa. Di tengah suasana yang mendidih itu, Abdul Muththalib memantapkan keputusan: undian harus menentukan siapa yang dipilih. Ia menoleh kepada penjaga berhala dan memerintahkannya dengan suara tegas:
“Wahai orang tua, keluarkan tempurungmu. Kocoklah di dalamnya nama anak-anakku itu. Biarkan Tuhan memilih siapa yang dikehendaki-Nya. Aku telah bernazar untuk menyembelih salah satu dari mereka sebagai persembahan kurban kepada Tuhan. Tentukanlah siapa yang akan dikurbankan, sebab aku belum menentukannya saat bernazar.”
Kerumunan menahan napas. Kota Mekkah seolah menunggu satu nama—dan satu nasib—jatuh dari tempurung undian itu.
Nama Abdullah Keluar Sebagai Undian
Sejak awal, pelayan berhala tidak pernah membayangkan tempurung undian akan dipakai untuk menentukan siapa yang darahnya harus tertumpah. Yang ada di kepalanya hanya upah—seratus dirham—dan pekerjaan yang harus segera selesai.
Dengan wajah dingin ia membawa tempurung, menatap kerumunan yang mengepung. Tatapan-tatapan keras dan wajah-wajah yang berbau bahaya membuat tangannya gemetar, meski ia berusaha menyembunyikannya. Ia mendekati putra-putra Abdul Muththalib, membuka tempurung tanpa sepatah kata, lalu menyodorkannya.
Satu per satu, putra-putra Abdul Muththalib memasukkan undian bertuliskan nama mereka. Tempurung ditutup, lalu dikocok kuat-kuat sampai dadu kayu di dalamnya benar-benar teracak. Napas orang-orang tertahan; mata membesar; air mata jatuh tanpa bisa dicegah.
Di antara mereka berdiri Abdullah, yang paling tampan—dan justru karena itu, banyak hati bergetar takut bila namanya yang keluar.
Pelayan itu mengocok lagi. Wajahnya masam; batinnya menolak pekerjaan ini. Ia merasa seperti sedang menggerakkan pisau ke leher seorang pemuda.
Dalam hati, ia seperti ingin berteriak kepada Hubal:
“Mengapa Engkau diam? Mengapa Engkau tidak bergerak? Mengapa Engkau tidak berbelas kasih kepada para pemuda itu dan menyelamatkan mereka dari perbuatan keji ini?
Kami mengerti Engkau adalah Tuhan yang penyayang dan berhati lembut. Bagaimana mungkin Engkau merestui darah seorang pemuda tak berdosa ditumpahkan di hadapanmu? Dia suci tak bersalah; hanya karena seorang ayah terlanjur bernazar—nazar yang tersulut amarah dan kekesalan—hingga terucap ketika ia menggali sumur Zamzam.
Mengapa Engkau tidak memerintahkan pelayan-pelayan-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu, seandainya Engkau benar-benar Tuhan? Agar mereka menjauhkan pisau besar dari tangan Abdul Muththalib, membebaskannya dari perbuatan keji yang hendak ia rintis dan jadikan tradisi bagi bangsa Arab sejak hari ini?”
Di tengah kerumunan, Aminah menangis. Ia menatap berhala bisu yang tak mampu memberi jawaban, dan keyakinannya makin menguat: betapa rapuhnya bergantung pada batu yang tak sanggup menolong siapa pun—bahkan dirinya sendiri.
Akhirnya, pelayan itu memasukkan tangan ke tempurung. Ia keluarkan satu undian, menatapnya berkali-kali, lalu berseru gagap:
“Abdullah.”
Kerumunan seketika bergemuruh. Teriakan protes melesat ke udara; banyak orang menuduh undian curang dan menuntut pengulangan. Namun Abdullah tersenyum—tenang, seolah menerima takdir. Ia menatap ayahnya dan berkata dengan suara tegas:
“Wahai ayahku! Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Pisau sudah berada di tanganmu, dan leherku di depanmu. Engkau tidak akan mendapati kegusaran pada diriku.
Potonglah, wahai ayahku, dan jangan bimbang. Jangan bersikap lemah di hadapan anakmu. Puaskan dirimu dan juga Tuhanmu.”
Saudara-saudara Abdullah ikut memprotes, menuntut undian diulang. Sebagian bahkan menawarkan diri—seakan ingin menukar leher mereka demi keselamatan Abdullah. Tetapi Abdul Muththalib tidak mengindahkan hiruk-pikuk itu. Ia menggenggam pisau lebih kuat, lalu maju membawa Abdullah ke hadapan Hubal. Tangis perempuan, ratapan, dan kebekuan para lelaki menyatu dalam satu suasana yang mencekik.
Saat Abdullah maju menyerahkan lehernya, tiba-tiba seorang gadis menerobos kerumunan. Dengan berani ia berdiri di depan Abdul Muththalib dan berteriak:
“Potonglah aku, wahai ayahku! Dan tinggalkan Abdullah.”
Abdul Muththalib murka:
“Apa yang terjadi padamu, wahai Ummu Hakim, sampai engkau menghalangiku dari perbuatan ini? Apakah engkau hendak menggugurkan perintah Allah?”
Ummu Hakim menjawab lantang:
“Melainkan aku datang menyelamatkan saudaraku, membiarkan hidup putra kesayanganmu, dan menyelamatkan dirimu sendiri. Hatimu akan hancur sepeninggal Abdullah, dan aku yakin engkau tidak akan bertahan lama setelah menyembelih putra tercintamu.”
Lalu ia menegaskan, suaranya meninggi:
“Aku dan Abdullah adalah saudara kembar. Maka sembelihlah aku sebagai ganti dia. Dan korbankan aku jika memang harus ada korban dari manusia. Bukankah aku juga manusia, wahai ayahku?”
Abdul Muththalib menolak keras:
“Namun, nazarku haruslah seorang laki-laki, bukan perempuan, wahai Ummu Hakim!”
Ummu Hakim membalas tanpa gentar:
“Demi Tuhan, wahai ayahku, Tuhan tidak akan merestui pembunuhan orang yang tak berdosa.”
Keberanian Ummu Hakim membangunkan nyali banyak lelaki. Tiga pria kuat melompat maju dan mencengkeram pisau besar itu. Mereka berseru:
“Kami tidak akan membiarkan engkau membunuh anak dari saudara perempuan kami! Potonglah orang selain dia jika engkau menghendaki. Masih banyak orang selain Abdullah!”
Abdul Muththalib membalas, tetap keras:
“Tapi ini kehendak dan perintah Tuhan, dan aku tidak akan melanggarnya. Tempurung undian telah mengeluarkan nama Abdullah; maka dialah yang harus disembelih.”
Ketiga pria itu mencengkeram pisau lebih kuat dan mengejek keyakinan pada undian:
“Dan apakah tempurung undian selalu benar? Kami sering memakainya, dan sering pula ia salah. Ia menyuruh kami berangkat ketika kami sedang menimbang perjalanan, tetapi yang kami dapat hanya letih. Ia memerintahkan kami berperang, tetapi hasilnya kekalahan telak. Betapa banyak derita manusia akibat kesalahannya. Lalu apa yang diperoleh Tuhan dari Abdullah dan darah Abdullah?”
Keributan memuncak. Abdul Muththalib berusaha merebut pisaunya, tetapi gagal. Tak seorang pun maju membantunya. Dalam ketidakberdayaan, ia memandang pelayan berhala dan bertanya:
“Dalam perkara ini, apakah engkau memiliki pendapat lain?”
Dari kerumunan, suara-suara keras menyeruak, mendesak jalan lain:
“Carilah keputusan lain, wahai Abdul Muththalib. Tanyakan perkara ini kepada seorang dukun, laki-laki atau perempuan. Barangkali ada jalan keluar yang menyelamatkan pemuda ini dan yang lain, serta menjauhkan pertumpahan darah manusia dari Rumah Allah yang aman ini.”
Akhirnya, Abdul Muththalib tunduk pada desakan massa. Keributan perlahan mereda, dan ia pun bersiap mencari keputusan lain—entah untuk menemukan jalan keluar yang diridai, atau kembali pada niat awalnya menyembelih Abdullah.
Solusi: Tetap Undian
Keesokan pagi, rombongan para pembesar Quraisy bergerak ke arah utara. Mereka mengejar secercah harapan: meminta keputusan seorang dukun perempuan di Hijaz, dekat Khaibar, yang reputasinya masyhur sebagai “pemecah perkara ketika akal buntu”.
Dua puluh hari kemudian, rombongan kembali ke Mekkah membawa solusi—bukan pembatalan nazar, melainkan jalan tebusan yang diuji melalui undian. Dukun itu lebih dulu menanyakan kebiasaan Quraisy tentang tebusan pembunuhan. Mereka menjawab: sepuluh ekor unta.
Maka sang dukun memberi aturan: letakkan Abdullah dan sepuluh ekor unta sebagai pilihan undian. Jika undian jatuh pada unta, Abdullah selamat. Jika jatuh pada Abdullah, tambah sepuluh ekor unta—dan ulangi—hingga undian memilih unta.
Solusi ini menyalakan harapan, sekaligus memantik ketakutan. Orang-orang bertanya-tanya: siapa yang dapat menjamin undian akan berhenti pada unta? Sebagian bahkan mencibir, takut harta Abdul Muththalib akan habis.
Namun di balik kegelisahan itu, Quraisy dan Bani Abdul Muththalib diam-diam bersepakat: jika keadaan memaksa, mereka akan menahan tangan Abdul Muththalib agar tidak menyembelih anaknya, apa pun hasil undian.
Malam itu Mekkah kembali terjaga. Di banyak rumah, lampu tetap menyala, doa tidak putus. Aminah menangis di rumah, sama gelisahnya dengan Fathimah (ibu Abdullah), para saudari, para kerabat, dan para perempuan yang takut kehilangan.
Keesokan siang, orang-orang berlari kecil menuju Ka’bah. Di sisi Haram, unta-unta gemuk telah dikumpulkan—gelisah, bersuara, mondar-mandir di balik tali. Pandangan massa bolak-balik antara unta-unta itu dan Hubal, berharap “tuhan-tuhan” memilih tebusan, bukan manusia.
Abdul Muththalib datang membawa pisau besar. Putra-putranya mengiringinya. Abdullah berdiri di sisi kanannya, tersenyum tenang—seolah menuju pelaminan, bukan maut.
Di depan Hubal, Abdul Muththalib berdoa. Lalu sepuluh ekor unta dipisahkan, dan pemilik tempurung undian diminta mengundi: Abdullah atau unta.
Tempurung dikocok. Kerumunan menahan napas. Undian pertama keluar:
“Abdullah.”
Kerumunan terguncang. Ada yang berbisik pahit, seolah takdir sudah ditutup rapat.
Lalu massa mendesak, dan Abdul Muththalib mengangguk: tambah sepuluh unta. Undian diulang untuk dua puluh unta. Hasilnya:
“Abdullah.”
Kegaduhan membesar. Teriakan bersahut-sahutan:
“Tambahkan! Tambahkan sepuluh! Jangan berhenti!”
Undian berlanjut. Tiga puluh. Empat puluh. Lima puluh—nama Abdullah terus muncul. Harapan banyak orang retak. Namun kelompok lain—fakir miskin dan yang kelaparan—justru menunggu tebusan membengkak, membayangkan jamuan daging yang akhirnya dapat mereka kecap.
Ketika undian mencapai sembilan puluh unta, ketegangan seolah memaku semua orang. Pemilik tempurung memandang Abdullah dengan iba, dan massa memekik meminta jumlah dibulatkan:
“Jadikan seratus! Tambahkan lagi!”
Abdul Muththalib memberi isyarat. Undian dikocok untuk seratus unta dan Abdullah. Suasana mendadak senyap; orang-orang diam seolah seekor burung mengintai di atas kepala mereka.
Pemilik tempurung memasukkan tangan yang gemetar, menggenggam satu undian, lalu membukanya. Kerumunan sempat meledak lebih dulu, menyangka hasilnya kembali buruk:
“Tambahkan, wahai pelayan! Tambahkan bilangannya! Abdullah tidak boleh disembelih!”
Namun setelah menarik napas panjang, si pemilik tempurung mengangkat suara setinggi-tingginya:
“Unta! Seratus!”
Seperti pecah bendungan, orang-orang memeluk Abdullah. Tangis berubah menjadi sorak. Mereka merangkul Abdul Muththalib, menciumi kepalanya, menepuk pundaknya. Abdul Muththalib berdiri lemas—lalu seakan sadar sepenuhnya, ia mengangkat suara dan memerintah:
“Sembelihlah unta-unta itu dan jadikan jamuan atas nama Tuhan! Tidak seorang pun dihalangi darinya. Burung dan hewan pun dipersilakan menikmatinya.”
Kabar itu segera diantar ke rumah Aminah. Mendengarnya, Aminah seakan hidup kembali: ia mengangkat kedua tangan, bersyukur, dan menanti Wuhaib pulang dengan rincian peristiwa—peristiwa yang mengubah ketetapan tebusan menjadi seratus unta.
Tunangan dan Pernikahan
Pisau-pisau besar bekerja tanpa henti. Unta-unta tebusan disembelih, dagingnya dipotong, lalu dibagikan melimpah di luar Kota Mekkah. Fakir miskin dan orang-orang yang lama menahan lapar berlari mendekat, berebut bagian dengan wajah berseri. Para pendatang pun ikut mengambil porsi; mereka memasukkan daging ke kantong-kantong besar dan pulang dengan sorak gembira, seolah menerima rezeki yang turun tanpa diduga.
Sementara itu, di rumahnya, Fathimah—ibu Abdullah—duduk dikelilingi putri-putrinya. Para perempuan datang berbondong-bondong mengucapkan selamat atas keselamatan Abdullah. Fathimah menangis lega, dan para tamu menenangkannya dengan kata-kata yang menyejukkan:
“Bergembiralah, wahai Fathimah, atas martabat luhur yang akan diraih putramu. Sungguh Tuhan tidak menghendaki keburukan baginya, melainkan menguji dia dan ayahnya—sebagaimana Ismail dan ayahnya. Tuhan hendak membuktikan kepada manusia bahwa Abdullah adalah yang terbaik dan paling mulia di antara mereka; tak seorang pun mampu menandinginya.”
Para gadis pun tampil dengan perhiasan termewah. Mereka mengucapkan selamat sambil berharap Abdullah terpikat pada kilau penampilan mereka. Namun saat itu, Abdullah dan ayahnya telah menuju permukiman Bani Zuhrah. Wuhaib—pemuka Bani Zuhrah sekaligus wali Aminah—telah lebih dulu sampai. Halah pun mendahului rombongan.
Di rumah Wuhaib, Halah mendapati Aminah berdiri di balik pintu, tegang mengikuti kabar dari Ka’bah. Halah memeluknya erat, mencium kedua pipinya berkali-kali, lalu berkata dengan mata berkaca-kaca oleh bahagia:
“Sudah saatnya aku menyampaikan kepadamu sebuah rahasia, wahai Aminah.”
Halah menggandeng Aminah masuk. Namun sebelum ia menjelaskan, Wuhaib datang. Ia memeluk Aminah dengan kasih, mencium pipi kanan dan kiri, lalu berkata lembut—namun tegas seperti seorang wali yang telah memantapkan keputusan:
“Aku telah menetapkan satu keputusan untukmu, wahai Aminah. Apakah engkau merestuinya?”
Aminah menunduk. Pipi gadis itu memerah, dan ia menangkap maksud pamannya tanpa perlu dijelaskan panjang. Halah tersenyum, seolah memastikan bahwa rahasia yang ia simpan akhirnya menemukan waktunya.
Tak lama, rombongan tamu tiba. Wuhaib keluar menyambut Abdul Muththalib, putra-putranya, dan para pemuka Quraisy. Di ruang tamu, Wuhaib menyatakan restu: Aminah dipinang untuk Abdullah. Dua keluarga sepakat tentang mahar dan waktu pernikahan; Abdul Muththalib meminta agar pesta disegerakan, dan Wuhaib mengiyakan.
Saat itu juga, Halah—yang melihat Aminah masih menunduk karena malu—mengangkat kepala Aminah dengan lembut dan berkata di hadapan Wuhaib:
“Semoga Allah memberkahimu, wahai Ayah. Abdullah adalah pemuda yang paling layak bagi Aminah, dan Aminah adalah perempuan yang paling layak bagi Abdullah.”
Kabar itu menyebar cepat ke seluruh Mekkah. Rumah Abdul Muththalib dan rumah Wuhaib didatangi orang-orang yang mengucap selamat. Ada yang benar-benar bahagia, ada yang terkejut, ada pula yang menelan kecewa karena harapannya runtuh. Para pemuda bersedih; mereka yakin suatu hari dapat meminang Aminah, namun kini semuanya selesai.
Malam Mekkah hidup sampai pagi. Di rumah Wuhaib, perempuan-perempuan memenuhi ruangan dengan obrolan, doa, dan nyanyian. Di sekitar Ka’bah, para lelaki membicarakan dua peristiwa yang menggetarkan kota: keselamatan Abdullah dan pernikahan yang dianggap “paling serasi”.
Persiapan pesta pun dimulai. Di banyak sudut kota, periuk-periuk mendidih; sisa-sisa jamuan menyebar hingga ke pinggir bukit, bahkan menjadi santapan binatang malam. Menurut kebiasaan Quraisy, Abdullah tinggal tiga hari di rumah Wuhaib. Sebuah kamar khusus disiapkan bagi keduanya. Hari-hari itu mereka jalani dalam teduh bahagia: menata masa depan, menyusun harapan, dan menutup jarak yang lama disimpan oleh tradisi dan rasa malu.
Pada hari keempat, Abdullah pulang ke rumahnya. Ibunya dan saudari-saudarinya telah menata rumah: wangi gaharu memenuhi sudut-sudutnya, makanan disiapkan, nyanyian sambutan terdengar. Abdullah menatap rumahnya dengan puas, lalu berkata dengan senyum halus:
“Yang tersisa hanyalah pengantin perempuan. Dialah yang akan menambah keindahan rumah kecil ini.”
Menjelang malam, Aminah dipersiapkan. Ia mengenakan sutra Yaman yang berhias indah, lalu berselimut pakaian hitam. Wajahnya ditutup cadar. Para pembantu membawa barang-barang ringan, dan rombongan Bani Zuhrah mengantarnya ke rumah Abdullah.
Fathimah menyambut Aminah dengan pelukan dan ciuman. Putri-putrinya turut memuliakan sang pengantin. Ketika Aminah masuk kamar dan membuka cadarnya, cahaya kecantikannya seakan memenuhi rumah. Serentak perempuan-perempuan berseru:
“Masya Allah! Masya Allah!”
Para tamu lelaki diterima Abdul Muththalib dengan doa perlindungan dari hasad dan keburukan. Obrolan berlangsung hingga larut, kemudian para tamu mundur, meninggalkan kedua pengantin.
Dalam sunyi yang hangat, Abdullah berkata lembut:
“Selamat datang di rumahmu yang baru, wahai Aminah.”
Aminah menjawab dengan senyum yang tenang:
“Selamat datang di kehidupanmu yang baru, wahai Abdullah.”
Malam berlalu dengan cerita-cerita kecil yang menguatkan hati, hingga pagi menerangi bumi. Abdullah pergi bertawaf dan bersyukur, lalu menziarahi ibunya sebentar dan menyapa ayahnya, sebelum kembali pulang.
Di rumah, Aminah telah bangun. Abdullah menatapnya lama, seakan melihat sesuatu yang baru. Aminah tersenyum dan menggoda dengan halus:
“Seakan-akan engkau sedang memandang pengantin baru, wahai Abdullah—seolah ingin menemukan sesuatu yang belum engkau ketahui.”
Abdullah menahan senyum, lalu berkata lirih:
“Tambahkanlah cahaya pagi ini, wahai Aminah. Semoga rumah kita lebih sejuk dan menenteramkan daripada rumah Bani Zuhrah.”
Aminah menunduk malu, lalu mengangkat mata dan berkata pelan—seolah menghubungkan tatapan suaminya dengan mimpi yang ia bawa sejak fajar:
“Cahaya baru apa yang engkau lihat, wahai Abdullah? Barangkali itu cahaya yang kulihat menjelang subuh. Aku bermimpi: cahaya yang sangat terang berpindah darimu, singgah dalam diriku. Lalu dari diriku keluar cahaya yang lebih terang, menyebar menerangi seluruh alam. Cahaya itu memusnahkan gelap dan menerangi setiap sudut bumi. Manusia terbangun, terkesima, lalu bersorak gembira. Apa makna cahaya itu, wahai Abdullah? Aku terbangun dan mimpi itu masih jelas di benakku. Apakah itu pula yang engkau lihat pada wajahku pagi ini?”
Abdullah terdiam sejenak, mencari makna yang menenteramkan. Lalu ia menjawab dengan keyakinan yang menyejukkan:
“Insya Allah, itu pertanda baik dan penuh berkah. Cahaya yang indah. Masa depan yang cemerlang, dan kehidupan yang lapang serta bahagia.”
Aminah menjadi lebih tenang. Ia menyiapkan sarapan. Abdullah memakannya dengan kagum, mencicipi manisan dan hidangan lain yang lezat. Aminah tersenyum, lalu berkata sambil mengingat pujian lama:
“Ayahmu, Abdul Muththalib, pernah berkata, ‘Apa pun yang dibuat oleh tangan Aminah pasti enak.’”
Mereka tertawa pelan. Setelah itu Abdullah pergi menemui para pemuka Quraisy yang tengah bermusyawarah soal dagang, sementara Aminah dan Barakah menyelesaikan urusan rumah dengan hati ringan.
Perpisahan Sang Pengantin
Kota Mekkah gegap gempita melepas rombongan pedagang yang bersiap berangkat ke Negeri Syam. Barang-barang dagangan ditata dan dihitung: parfum, rempah-rempah, kain Yaman, barang-barang dari India dan Habasyah, kurma Hajar, serta berbagai komoditas lain yang laris di utara. Penduduk berkumpul membicarakan perniagaan—tentang modal titipan, keuntungan, dan siapa yang pandai memutar barang hingga berlipat hasilnya.
Di sekitar Ka’bah, para pedagang senior dan pemuka Quraisy memberi wejangan: rute singgah, tempat transaksi yang menguntungkan, tanda-tanda bahaya, cara membaca wajah pembeli, hingga ungkapan-ungkapan dagang yang halus namun mengikat. Mereka juga mengingatkan tentang pajak Romawi di Syam—tarif yang kerap mencekik dan perilaku aparat yang sewenang-wenang. Pedagang-pedagang kawakan bercerita dengan bangga tentang keberhasilan mereka; sebagian jujur apa adanya, sebagian lain memperbesar kisah, menghiasnya dengan bumbu yang memikat. Para pedagang pemula menyimak dalam diam, seolah menorehkan semua pelajaran itu ke dalam ingatan.
Di tengah keramaian itu, Abdul Muththalib duduk tenang—berpikir panjang. Putra-putranya menunggu keputusan siapa yang akan memimpin rombongan dagang keluarga. Ketika akhirnya ia mengangkat wajah, pandangannya jatuh pada Abdullah. Ia menutup mata sesaat, lalu berkata dengan suara lembut namun tak terbantahkan:
“Wahai Abdullah! Engkau belum pernah melakukan perjalanan ke Yaman pada musim dingin, maupun perjalanan ke Syam pada musim panas, serta perjalanan-perjalanan lain yang keluar-masuk Mekkah. Sudah saatnya engkau mengenal negeri-negeri ciptaan Allah dan belajar dari luasnya kehidupan.
Aku memutuskan engkaulah yang akan berangkat pada perjalanan kali ini: membawa harta Bani Muththalib dan harta titipan orang-orang yang kau urus. Tak seorang pun meragukan kecakapanmu, kecerdasan usahamu, dan keluwesanmu. Insya Allah, dengan pertolongan Allah, engkau akan pulang membawa keuntungan yang melimpah.”
Wajah Abdullah menahan gelombang batin. Pikirannya langsung melayang kepada Aminah: bagaimana ia akan menyampaikan kabar ini, sementara aroma pernikahan mereka bahkan belum reda. Abdul Muththalib menangkap kegamangan itu, lalu menutup pembicaraan dengan kalimat yang seperti palu mengetuk keputusan:
“Berdirilah, wahai Abdullah. Siapkan bekal perjalananmu. Allah telah menetapkan kehendak-Nya.”
Abdullah pulang dengan langkah yang tampak tegak, tetapi pikirannya sesak. Di rumah, ia berusaha menebarkan senyum—namun Aminah membaca gelisah yang ia simpan. Dengan suara lembut penuh perhatian, Aminah menyapanya:
“Berlakulah baik, wahai Abdullah. Ada apa denganmu? Engkau keluar diiringi kebahagiaan, tetapi pulang membawa kegelisahan.”
Abdullah menatapnya lama, lalu membuka rahasia itu perlahan—seakan takut kata-katanya melukai:
“Baik-baik saja, wahai Aminah. Ini undangan meraih rezeki dari Abdul Muththalib: perjalanan dagang ke Negeri Syam.”
Aminah tersenyum, menahan rasa perih agar tidak menular sebagai ketakutan. Ia memilih menguatkan, bukan merintih:
“Lalu adakah orang menolak rezeki dan menjauhkan kebahagiaan? Pergilah dengan berkah Allah. Engkau akan kembali selamat dan membawa banyak keuntungan. Abdul Muththalib menghendaki kebaikan bagimu. Ia melihat engkau telah berkeluarga; hidup dan masa depan menuntutmu berusaha dan menempuh perjalanan.
Dalam perjalanan, wahai Abdullah, ada banyak faedah: mencari rezeki, mengasah pikiran, memahami luasnya dunia, bergaul dengan manusia, memperluas wawasan, dan belajar bersama orang-orang terpilih dalam perniagaan yang menghadirkan kehormatan.”
Aminah bahkan menyebut nama-nama pedagang besar Mekkah yang dulu berangkat sebagai saudagar biasa dan pulang sebagai orang terpandang. Abdullah mendengarkan, tetapi resahnya belum luruh. Dengan lirih ia mengakui apa yang sebenarnya menahannya:
“Ketika Abdul Muththalib menyampaikan perintah itu kepadaku, aku langsung teringat kepadamu, wahai Aminah. Aku ingin mengundurkan diri karena dirimu.”
Aminah cepat menjawab—tegas, seolah menahan Abdullah agar tidak jatuh ke dalam alasan yang kelak mempermalukannya:
“Mengapa, wahai Abdullah? Tidakkah engkau ingin menjadi orang kaya, berharta melimpah? Semua mata memandang kepadamu. Mereka yakin engkau kelak memimpin Mekkah menggantikan ayahmu. Mereka akan menaruh beban besar di pundakmu—untuk kaum, keluarga, bahkan bangsa Arab. Itu semua lebih mudah dipikul bila engkau kuat dalam usaha dan rezeki.
Kehormatan di Mekkah sering diraih oleh orang kaya yang dermawan: menolong yang lemah, melunasi utang orang susah, dan memuliakan sanak kerabat.”
Abdullah menahan air mata. Ketakutannya bukan tentang uang atau pasar; ketakutannya tentang kehilangan yang baru saja hampir ia alami:
“Lalu apa dosamu, wahai Aminah? Engkau akan tinggal sendiri sebagai pengantin baru. Dan siapa yang tahu, wahai Aminah? Sekali di bawah ketajaman pedang, sekali di tengah padang pasir dan gunung-gunung!”
Aminah memaksa hatinya berdiri tegak, lalu menjawab dengan keyakinan yang ingin ia tanamkan ke dada suaminya:
“Apakah engkau takut, wahai Abdullah? Siapakah yang menyelamatkanmu dari pisau ayahmu dan menebusmu dengan seratus unta? Dia pula yang akan menyelamatkanmu dari segala mara bahaya. Bila Allah menghendaki keburukan bagimu, niscaya Dia tidak menerima tebusan itu.
Maka teguhkan hatimu, wahai Abdullah. Jadilah pemberani. Perjalanan dagang bukan hal baru bagi bangsa Arab; itu tradisi Quraisy dan para kesatria. Ada untung dan rugi, ada lelah dan bahaya—tetapi itulah jalan kehormatan.
Apa arti hidup tanpa usaha dan pengorbanan? Hidup yang hambar, tak berwarna, seperti kehidupan orang yang tak memiliki apa-apa dan mengais sisa-sisa makanan. Sekaya apa pun seseorang, ia tak merasakan makna hidup bila mengurung diri dalam kenyamanan tanpa gerak.
Relakah engkau bila orang berkata: ‘Abdullah bin Abdul Muththalib mundur dari perjalanan karena takut’? Relakah engkau bila dikatakan: ‘Ia melemah karena perempuan, tak sanggup menanggung urusan lelaki dan tradisi para kesatria’?”
Lalu Aminah menggenggam tangan Abdullah—kali ini bukan sebagai istri yang meminta, tetapi sebagai istri yang mengantar:
“Jangan pikirkan Aminah, wahai Abdullah. Pikirkan beban besar di hadapanmu. Urus masa depanmu. Engkau akan memperluas rumah ini, menambah pelayan, memuliakan keluarga, dan kelak orang-orang menempatkanmu di posisi terhormat.
Adapun ajal berada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Singkirkan kegelisahan dan buang jauh keraguan. Siapkan bekal perjalananmu. Aminah akan selalu hidup bersamamu dalam kalbu. Bayanganmu tentang rumah ini akan menenangkanmu, dan bayangan itu akan lebih membahagiakanku ketika aku membayangkan engkau memimpin rombongan dagang dengan keberanian.”
Belum selesai Aminah menambah penguatan, terdengar ketukan keras di pintu. Suara itu memanggil Abdullah agar segera datang ke majelis Quraisy, memenuhi perintah Abdul Muththalib. Abdullah pergi—dan Aminah yang baru saja tampak tegar, tiba-tiba harus melawan pikirannya sendiri: rute berbatu, jalan terjal, pembegal, binatang buas, dan panas yang tak berbelas kasihan.
Di Ka’bah, Abdullah menerima barang titipan, menghitungnya satu per satu. Abdul Muththalib menyaksikan dari jauh—terlihat tegar, tetapi sesekali cemas menyusup, lalu ia mengusirnya dengan doa.
Malam berakhir. Menjelang fajar, suara panggilan keberangkatan menggema. Abdullah menatap Aminah lama. Air matanya nyaris jatuh, sementara Aminah menahan diri agar tidak runtuh di hadapannya. Abdullah melangkah keluar perlahan; Aminah mengikutinya dengan pandang yang tak ingin melepas, sampai sosok itu lenyap dari pintu.
Aminah menutup pintu. Kesunyian menyerbu rumah seperti gelombang. Ia berjalan tanpa tujuan, bersandar pada dinding. Barakah, pelayannya, setia menemani—namun kata-kata pun terasa tidak cukup. Akhirnya Aminah masuk ke kamar, merebahkan diri, dan tangisnya pecah dalam diam yang panjang: perpisahan pertama yang terasa terlalu cepat untuk hati yang baru belajar tenang.
Ucapan Terakhir Abdullah
Rombongan kafilah mulai bergerak. Unta-unta bergoyang di bawah beban barang, lalu perlahan menjauh dari Kota Mekkah. Teriakan perpisahan terdengar bersahut-sahutan; tangan-tangan melambai panjang. Sebagian orang memanjat gunung agar dapat melihat rombongan lebih lama. Dari puncak, kafilah tampak seperti garis tipis yang merayap di padang pasir—semakin lama semakin pudar, lalu lenyap. Mereka turun dengan mata basah, pulang dengan langkah lemah.
Barakah kembali ke rumah dan menjumpai Aminah di kamar, sendirian, larut dalam tangis. Ia duduk tidak jauh, lalu menceritakan bagaimana Abdullah menahan diri di hadapan ayah dan ibunya—berusaha tampak tegar, meski perpisahan itu menekan dada. Barakah menyebut keberanian dan ketampanan tuannya, namun Aminah baru benar-benar runtuh ketika Barakah mengulang kalimat terakhir Abdullah—bisikan yang dititipkan kepadanya sebelum rombongan bergerak:
“Jagalah permaisuriku, wahai Barakah. Bantulah ia menahan perpisahan ini. Jauhkan ia dari segala kegelisahan, dan jangan biarkan kesedihan menjarahnya. Aku berharap berhasil dalam perniagaan ini dan kembali kepadanya dengan buah-buahan dan barang-barang terbaik dari Negeri Syam: kain tenun yang indah dan perhiasan yang memperindah dadanya—meski ia tak memerlukannya. Dan aku tidak akan melupakanmu, wahai Barakah. Akan kubawakan hadiah berharga untukmu.”
Aminah menangis lebih deras. Barakah melanjutkan, suaranya ikut bergetar:
Ia melihat Abdullah memalingkan wajah agar air matanya tak terlihat. Lalu Abdullah menaiki untanya dan menyatu dengan rombongan—hingga ditelan hamparan pasir yang luas.
Aminah menatap sudut ruangan seolah di sana terbuka jalan panjang yang dilewati kafilah. Dalam khayalnya, ia melihat Abdullah berjalan cepat ketika rombongan cepat, berjalan pelan ketika rombongan melambat. Di antara air mata, sempat muncul senyum tipis—senyum yang lahir dari rindu yang belum sempat matang.
Barakah terdiam. Ia melihat tuan putrinya seolah meninggalkan Mekkah dengan ruhnya; tubuh Aminah tinggal di ranjang, tetapi hatinya berjalan bersama kafilah melewati gunung dan lembah.
Tiba-tiba Aminah menatap Barakah, memejamkan mata, lalu berkata pelan namun tegas:
“Ulangi lagi ucapan terakhir Abdullah, wahai Barakah.”
Belum sempat Barakah menjawab, terdengar ketukan di pintu. Aminah cepat mengusap air mata dan berusaha menegakkan diri. Barakah membuka pintu: Abdul Muththalib, Fathimah (ibu Abdullah), dan Halah binti Wuhaib berdiri di ambang.
Mereka masuk dengan senyum yang dipaksakan—berusaha menutupi duka, tetapi raut wajah justru membocorkan apa yang mereka tahan. Fathimah dan Halah duduk di sisi Aminah; Abdul Muththalib duduk sedikit menjauh, memandang Aminah dengan lembut, lalu berkata menenangkan:
“Abdullah bersikeras bangkit meraih kemuliaannya, wahai Aminah. Ia pergi sebagaimana orang-orang Quraisy: menembus cakrawala, mengenali manusia, mencari sumber-sumber rezeki, lalu memetiknya dengan usaha.
Dengan pertolongan Allah, ia akan kembali selamat dan membawa banyak keuntungan. Jalan telah aman; setiap jengkalnya dikenal oleh Quraisy. Ia akan singgah di rumah sahabat dan kerabat kita. Mereka memuliakan kita, menjaga kafilah, dan sebagian dari mereka akan berjalan bersama rombongan hingga ke Syam.”
Abdul Muththalib berhenti sejenak, seolah menata ingatan, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih personal:
“Beginilah Abdul Muththalib tumbuh dewasa, wahai Aminah. Tidakkah engkau mengetahuinya? Aku dilahirkan dan dibesarkan di Yatsrib, dan paman-pamanku di sana adalah para pembesar Bani Najjar.
Yang mungkin belum engkau ketahui: ayahku, Hasyim bin ‘Abd Manaf, dimakamkan di Gaza, Negeri Syam. Ia berangkat dalam perjalanan dagang; di sana ia sakit, lalu wafat, dan dimakamkan di Gaza. Kelak tempat itu dikenal sebagai Gaza Hasyim.”
Ucapan itu—walau diniatkan sebagai kisah—justru menambah luka. Abdul Muththalib sendiri menitikkan air mata. Aminah pun menangis, dan pikirannya meloncat ke bayangan paling menakutkan: Abdullah mengikuti jejak Hasyim—pergi dan tak kembali. Abdul Muththalib segera sadar ia keliru memilih kisah. Ia mengusap air matanya dan berusaha mengubah arah pembicaraan agar menjadi penguat, bukan pemukul.
Dengan senyum yang dipaksakan, ia berkata:
“Namun Hasyim wafat setelah menunaikan tugas hidupnya. Ia orang pertama yang mengikat bangsa Arab dengan negeri-negeri besar melalui perjanjian tertulis. Ia membuat kesepakatan dengan Kaisar Romawi sehingga Quraisy dapat berdagang aman di wilayahnya. Ia juga mengamankan jalur dagang dari para pembegal dan menetapkan kesepakatan agar Quraisy membawa barang tanpa diperas upeti.
Ia pun membuat perjanjian dengan an-Najasyi, Raja Habasyah: Quraisy dapat masuk, berdagang, lalu pulang dengan aman.
Dan ketahuilah, wahai Aminah: Yatsrib itu indah. Aku berharap suatu hari engkau dapat mengunjunginya—pohon kurmanya tinggi, buahnya mudah dipetik, airnya tawar, udaranya sejuk.”
Lalu, seperti sengaja mengalihkan suasana, ia menambahkan kisah ringan dan tertawa kecil, memandang Fathimah dan Halah:
“Ibuku seorang perempuan Yatsrib bernama Salma. Ketika ayahku meminangnya, ia memberi syarat: ia ingin kebebasan menentukan kehendaknya; bila ia membenci suaminya, ia boleh menceraikannya.”
Fathimah dan Halah tersenyum—bukan karena kisah itu lucu, melainkan karena Abdul Muththalib berusaha keras mengangkat duka Aminah dengan apa pun yang bisa menjadi penyangga.
Abdul Muththalib menutup pertemuan dengan kalimat yang ingin ia tanamkan sebagai pegangan:
“Hari-hari berjalan cepat, wahai Aminah. Ia menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Siapkan dirimu menyambut pertemuan yang akan datang. Abdullah dalam lindungan Allah, dan bahaya tidak akan menyentuhnya.”
Mereka lalu berbincang tentang hal-hal yang mengundang senyum—kabar keluarga, cerita-cerita ringan, dan harapan-harapan baik—agar Aminah tidak ditelan sunyi. Setelah itu, mereka pamit, meninggalkan Aminah bersama kenangan yang manis sekaligus menyayat. Barakah tetap di dekatnya, berusaha menghibur semampunya.
Sejak hari itu, Abdul Muththalib hampir tak pernah absen: ia memulai hari dengan tawaf di Ka’bah dan menutupnya dengan mengunjungi rumah Abdullah—menengok Aminah. Fathimah dan Halah pun datang silih berganti, begitu pula keluarga Wuhaib. Mereka membawa hadiah kecil, kabar baik, atau sekadar humor sederhana.
Namun, ketika malam telah melewati separuhnya dan rumah kembali sunyi, Aminah kembali digenggam oleh rasa yang sama: sepi yang panjang, dan wajah Abdullah yang terus hidup di hatinya—seakan duduk di sampingnya, tetapi tak dapat disentuh.
Ia Tak Pernah Kembali
Hari-hari terus bergulir. Kota Mekkah tetap ramai, tetapi di dalam rumah Aminah suasananya sepi. Ia hidup di antara lamunan: bayangan Abdullah hadir di setiap bisikan, menemaninya saat terjaga maupun tertidur. Dalam mimpi, Abdullah kadang datang ceria; kadang tampak sakit dan mengaduh; kadang seolah betah tinggal di Syam atau Yatsrib, bahkan mengajak Aminah menyusul.
Para perempuan datang hampir setiap hari. Mereka berbincang panjang, mengadukan perkara rumah tangga dan urusan kecil yang bagi Aminah terdengar seperti suara jauh. Ia mengangguk, menyimak, tetapi pikirannya terus terbang dari Mekkah ke Syam—lalu kembali—kemudian terbang lagi, tak pernah benar-benar mendarat.
Namun, suatu pagi Aminah terbangun dengan perasaan berbeda. Ada ketenangan yang asing, seolah rumah berubah menjadi taman: bunga-bunga mekar dalam pandangan, dan buah-buah terasa dekat. Ia memanggil Barakah dan bertanya dengan tenang:
Aminah: “Sudah berapa hari sejak Abdullah berangkat, wahai Barakah?”
Barakah—yang sejak lama menahan cemas—tampak lega melihat wajah Aminah yang lebih lapang. Ia menghitung cepat dengan jari, lalu menjawab cerah:
Barakah: “Sudah lewat sebulan lebih, wahai tuan putriku. Dan sebelum sebulan lagi, wajah tuanku akan tampak kembali, pulang membawa keuntungan.”
Ia tertawa kecil, lalu menambahkan dengan nada bercanda yang khas, seolah ingin memancing Aminah ikut tersenyum:
Barakah: “Dan aku akan memakai pakaian indah seperti yang dijanjikan tuanku—biar para pembantu lain iri dan para penghasut makin panas.”
Barakah melangkah ke sana kemari, membayangkan hari kedatangan kafilah. Lalu ia berhenti di depan Aminah, penuh gairah:
Barakah: “Aku akan menunggu kafilah di luar kota, di titik terjauh. Aku tak sanggup menunggu sampai tuanku tiba di rumah. Aku ingin jadi orang pertama yang melihatnya, lalu aku berlari pulang membawa kabar paling indah untuk tuan putriku.”
Aminah menggeleng pelan. Senyumnya tipis, tetapi matanya menatap jauh ke arah utara, ke arah Syam. Suaranya turun, seperti menyimpan sesuatu yang belum ia ucapkan terang-terangan:
Aminah: “Semoga begitu, wahai Barakah. Hari-hari berjalan lambat dan terasa berat. Aku tidak tahu kabar apa yang disembunyikannya. Tapi malam ini aku merasa Abdullah telah meninggalkan sebuah amanat yang sangat berharga. Andai ia mengetahuinya, niscaya ia akan pulang secepat angin.”
Barakah paham isyarat itu. Matanya menggenang; bahagianya seperti tercampur haru.
Barakah: “Hanya beberapa hari lagi, tuan putriku. Tuanku akan datang dengan wajah berseri, bahagia menerima amanat itu. Kebahagiaan bertemu akan menyatu dengan kebahagiaan rezeki.”
Siang hari, para tamu kembali berdatangan. Percakapan berputar pada satu hal: kafilah Quraisy tak lama lagi tiba. Mendengar itu, jantung Aminah berdebar tak wajar. Dadanya sesak, air mata mengalir begitu saja. Para perempuan heran melihat ia menangis justru saat kabar kepulangan mendekat. Salah seorang menegurnya agak keras, seolah ingin menarik Aminah keluar dari gelombang takutnya:
Tamu: “Apa ini, wahai Aminah? Ini saat bahagia, bukan saat menangis. Esok engkau akan melihat Abdullah datang dengan ketampanan dan keselamatannya. Bangkitlah, bersiaplah. Kenakan pakaian pernikahanmu—engkau masih di masa-masa itu.”
Aminah menunduk. Suaranya tertekan, seperti orang yang mencoba menjelaskan sesuatu yang hanya ia rasakan sendiri:
Aminah: “Semua orang menghendaki keselamatan. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Hatiku gelisah. Aku tidak merasakan kebahagiaan yang mendekat. Aku justru merasakan sesuatu yang aneh akan terjadi.”
Mereka mencoba menenangkan, tetapi tak ada kata yang benar-benar menembus. Para tamu akhirnya pamit untuk bersiap menyambut keluarga masing-masing.
Malam itu Aminah nyaris tak tidur. Barakah duduk di sampingnya, ikut resah. Hingga fajar menyingsing, kota bergerak cepat seperti arus yang ditarik ke satu pusat: batas Mekkah—tempat kafilah akan masuk.
Barakah melesat keluar, cepat seperti kijang, ingin memastikan kabar. Aminah ditinggal sendirian di balik pintu, telinganya menajam. Ia mendengar hiruk-pikuk penyambutan dari kejauhan—namun semakin lama, tidak ada yang mengetuk pintunya. Barakah tak kembali. Abdullah pun tak datang.
Pertanyaan-pertanyaan berputar di kepalanya, menumpuk tanpa jawaban:
apakah Abdullah bertawaf di Ka’bah terlebih dahulu?
apakah ia singgah ke rumah ayahnya?
apakah ia ditahan urusan dagang?
lalu di mana Barakah—mengapa ia tak berlari pulang seperti janjinya?
Aminah hampir memutuskan pergi ke rumah Abdul Muththalib. Saat itu pula terdengar langkah-langkah pelan mendekat. Jantungnya seperti dipukul. Ketukan halus terdengar di pintu—tidak tergesa, tidak gembira. Aminah berkata setengah berdoa, setengah meyakinkan diri:
Aminah: “Kabar baik… kabar baik. Ketukan lembut dari tangan yang lembut. Ya Allah, siapa itu? Barakahkah?”
Saat pintu dibuka, Aminah tidak melihat Barakah dengan senyum, tidak pula Abdullah dengan wajah pulang. Yang berdiri di depan adalah Wuhaib beserta keluarganya, dan Abdul Muththalib bersama putra-putrinya serta para istri. Seketika tubuh Aminah melemah. Ia hampir jatuh. Para perempuan cepat menopang, menuntunnya ke kamar, membaringkannya, dan memberi pengobatan seadanya. Barakah—yang ternyata telah pulang bersama mereka—menjerit sambil menampar pipinya sendiri:
Barakah: “Jangan pergi, tuan putriku! Janganlah pergi!”
Saat Aminah siuman, ia membuka mata, mencari satu wajah yang tidak ada. Suaranya pecah oleh takut:
Aminah: “Di mana Abdullah? Ke mana ia pergi?”
Wuhaib mendekat, menahan diri agar suaranya tidak runtuh:
Wuhaib: “Ada apa, wahai Aminah? Tenanglah, putriku. Jangan takut seperti yang kau bayangkan. Abdullah baik-baik saja. Jika ia tidak datang hari ini, esok atau lusa ia akan datang.”
Lalu Abdul Muththalib berdiri. Nada suaranya lirih, terlalu lirih untuk meyakinkan orang yang sedang panik—tetapi ia memaksa tenang:
Abdul Muththalib: “Jangan takut, wahai Aminah. Hanya beberapa hari. Abdullah akan kembali selamat. Kabar yang kami terima: ia sedang sakit di Yatsrib, sehingga kepulangannya tertunda.”
Halah menimpali cepat, berusaha memberi warna harapan:
Halah: “Ia hanya kelelahan. Yatsrib udaranya sejuk. Ia tinggal bersama paman-pamannya, dirawat dan dijaga. Dengan izin Allah, ia akan sembuh dan pulang.”
Halah mengusap pipi Aminah, lalu mencoba menggoda lembut agar Aminah tidak jatuh terlalu jauh:
Halah: “Bangkitlah, wahai pengantin perempuan. Siapkan dirimu. Mungkin Abdullah sedang menguji kesabaran kita—ia ingin melihat apa yang kita lakukan saat ia terlambat.”
Namun Aminah tetap memandang Abdul Muththalib—menunggu kata yang lebih pasti. Abdul Muththalib pun berkata lagi, seolah ingin menutup celah ketakutan:
Abdul Muththalib: “Aku sudah mengutus saudara Abdullah, al-Harits, ke Yatsrib sejak kabar itu datang. Ia sedang memacu kudanya. Tidak lama lagi Abdullah akan kembali ke tengah-tengah kita.”
Selesai berkata, Abdul Muththalib memalingkan wajahnya—menyembunyikan genangan air mata. Itulah yang membuat hati Aminah bergetar: kebohongan sering berbunyi seperti ketenangan, tetapi air mata selalu jujur.
Para tamu pamit. Tinggallah Aminah dan Barakah dalam sunyi yang tak menolong. Setiap jam Aminah bertanya, berulang-ulang, seperti orang menggenggam kata agar tidak jatuh:
Aminah: “Apakah Abdullah akan kembali? Apakah ia benar masih hidup? Kau melihat ia akan pulang, wahai Barakah?”
Kota Mekkah kemudian hanya menyisakan satu pembicaraan: keterlambatan Abdullah, kesetiaan Aminah, dan kecemasan Abdul Muththalib yang dulu hampir memotong leher putranya sendiri.
Lalu al-Harits pulang membawa berita yang jatuh seperti petir: Abdullah wafat.
Setelah itu, air mata Aminah seperti mengering bukan karena sembuh, tetapi karena habis. Lidahnya kelu. Matanya kosong. Dunia gelap, orang datang dan pergi tanpa bentuk. Mereka berbisik: bila Aminah tetap seperti itu, ia akan menyusul Abdullah.
Hingga pada suatu pagi, Aminah terbaring lemah. Ia membuka mata, menatap sesuatu yang tak dilihat orang lain. Lalu ia memejam, menggeleng pelan, dan berkata lirih—seolah akhirnya mengerti:
Aminah: “Sekarang aku tahu di mana Abdullah. Sekarang aku tahu ke mana ia pergi.”
Kembali Pulih
Aminah mulai menyadari bahwa dirinya mengandung. Kesadaran itu datang bukan sebagai kabar biasa, melainkan sebagai suara batin yang menegakkan tubuhnya—seolah ada tangan lembut yang menahan bahunya agar tidak runtuh lebih lama.
Dalam diam, ia menasihati dirinya sendiri:
Aminah (dalam hati): “Tidak ada gunanya terus bersedih. Kegelisahan tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, dan penyesalan tidak dapat memutar waktu. Abdullah telah meninggalkan amanat yang sangat berharga. Aku harus menjaganya.”
Ia merasa Abdullah seakan diberi tugas di dunia—dan tugas itu kini berpindah ke dalam rahimnya. Bila Abdullah telah pergi menghadap Tuhan, maka tanggung jawab Aminah adalah menjaga warisan yang ditinggalkan: janin yang tumbuh dalam dirinya.
Ingatan Aminah melompat pada mimpinya setelah pernikahan: cahaya yang berpindah dari Abdullah ke dirinya, lalu menyebar luas. Sekarang ia menafsirkan ulang mimpi itu:
Aminah (dalam hati): “Barangkali inilah cahaya yang pernah kulihat. Aku tidak boleh tinggal dalam sakit dan air mata. Aku harus bangkit, tegar, mulai hari ini.”
Perubahan Aminah terlihat jelas. Wajahnya lebih segar, geraknya lebih tangkas, dan matanya tidak lagi seperti orang yang tenggelam. Justru itu membuat para perempuan heran. Mereka mulai berbisik—bukan karena membenci, melainkan karena tak mengerti.
Para perempuan (berbisik): “Apakah Aminah sudah melupakan Abdullah? Apakah ia akan menikah lagi, seperti perempuan lain yang ditinggal mati suami?”
Aminah tidak menanggapi. Hari-hari berjalan dan kehamilan kian besar. Ia merawat dirinya dengan ketenangan yang tidak lazim. Ia nyaris tidak merasakan keluhan yang biasa dialami perempuan hamil. Yang ia rasakan justru semacam kejernihan—seolah beban duka beralih menjadi kewajiban yang memberi arah.
Namun, setiap kali mendekati masa kelahiran, bayangan Abdullah kembali kuat. Ia membayangkan seandainya Abdullah masih hidup: ia akan tersenyum lebar menyambut kabar kelahiran anaknya, membagi hadiah, dan menjaga anak itu dengan kebanggaan seorang ayah.
Di sela-sela tidur, Aminah sering bermimpi berada di taman yang luas: ada sungai mengalir, angin lembut, bunga-bunga mekar, dan burung-burung bernyanyi. Di taman itu ia melahirkan seorang bayi laki-laki, tampan dan bercahaya.
Pada suatu malam, di dalam mimpi yang sama, ia mendengar bisikan yang jernih—bukan seperti khayal yang kabur, melainkan seperti pesan yang tegas:
Suara (dalam mimpi): “Bersiaplah, wahai Aminah. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Berilah ia nama Ahmad. Hanya beberapa hari lagi, dan engkau akan melihat cahaya yang sangat terang itu.”
Aminah terbangun dengan dada penuh harap. Ia ingin hari-hari bergerak lebih cepat. Dalam hatinya, ia berharap wajah anak itu kelak memantulkan sesuatu dari Abdullah—sekilas saja, cukup untuk menguatkan.
Pada waktu yang sama, Jazirah Arab diguncang kabar besar dari Yaman. Habasyah menguasai wilayah itu, dan Abrahah—penguasanya—membangun sebuah bangunan megah untuk menandingi Ka’bah. Ia ingin memindahkan pusat perhatian bangsa Arab dari Mekkah ke Yaman, sekaligus memutus jalur kehormatan dan perdagangan Quraisy.
Namun rencana itu gagal. Bangsa Arab tidak berpaling dari Ka’bah. Bahkan bangunan Abrahah dihina dan dinodai. Amarah Abrahah meledak. Ia bersumpah menghancurkan Ka’bah agar Quraisy jatuh bersama runtuhnya rumah suci itu.
Kabar pasukan Abrahah—dengan gajah besar di barisan depan—mendekat ke perbatasan Mekkah. Penduduk Mekkah panik dan berunding. Yang mengejutkan: Aminah justru lebih tenang daripada kebanyakan orang. Ia yakin rumah Tuhan tidak akan dibiarkan hancur.
Sementara itu, para lelaki Quraisy diliputi gelora: darah muda mendidih, para tua pun ingin mempertahankan kehormatan. Mereka mendesak Abdul Muththalib untuk memimpin perlawanan.
Namun Abdul Muththalib menatap Ka’bah dan langit dengan ketenangan yang membuat orang-orang salah paham. Saat sebagian orang tak tahan, mereka memprotes keras:
Kaum Quraisy: “Apa yang terjadi, wahai pemimpin Mekkah? Engkau tampak seolah menyerah! Demi Tuhan Ka’bah, kami akan melawan sampai habis! Mengapa engkau tenang seakan tak ada apa-apa?”
Abdul Muththalib menjawab tanpa meninggikan suara—jawaban yang memindahkan pusat pertahanan dari otot ke keyakinan:
Abdul Muththalib: “Apa yang mampu kita lakukan melawan pasukan sebesar itu? Rumah ini adalah rumah Allah. Jika manusia menjaga rumahnya, maka Allah lebih berhak menjaga rumah-Nya. Senjata-Nya lebih kuat daripada senjata kita, dan pasukan-Nya lebih besar daripada pasukan kita.”
Mereka masih mendesak:
Kaum Quraisy: “Lalu apa yang harus kami lakukan?”
Abdul Muththalib: “Keluarlah dari Mekkah. Pergilah ke tempat-tempat tinggi dan terpencil. Selamatkan diri kalian. Serahkan rumah ini kepada Pemiliknya.”
Akhirnya mereka patuh. Penduduk Mekkah mengosongkan kota. Aminah juga bersiap pergi setelah diyakinkan Abdul Muththalib—meski dalam hati ia percaya, tinggal pun tidak akan mencelakakannya.
Abdul Muththalib sendiri mendatangi Ka’bah. Ia memegang pintunya dan berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon agar Allah menjaga rumah-Nya.
Ketika Abrahah memasuki kota, ia terkejut melihat Mekkah kosong. Ia mengira itu tipu daya. Ia berteriak untuk menguatkan pasukannya:
Abrahah: “Jangan gentar! Ka’bah hanyalah bangunan. Tidak ada kekuatan yang dapat menahan kita!”
Ia memerintahkan pasukannya maju, gajah besar di depan barisan. Tetapi gajah itu tiba-tiba berhenti. Dipukul, dibentak, dipaksa—tetap tidak mau bergerak menuju Ka’bah. Anehnya, bila diarahkan ke kanan atau kiri, ia bergerak cepat; bila diarahkan mundur, ia semakin patuh. Tetapi begitu diarahkan ke depan, ia menggerang keras dan menolak.
Abrahah gelisah. Ia meninggalkan gajahnya dan memerintahkan pasukan menyerang.
Saat itulah langit menggelap oleh burung-burung kecil. Mereka berputar di udara, membawa batu-batu kecil, lalu menghujani pasukan Abrahah. Kekacauan pecah. Tentara yang angkuh berjatuhan, lari tunggang-langgang. Serangan itu menghancurkan barisan mereka—cepat, mematikan, tanpa mampu mereka lawan.
Ketika semuanya usai, penduduk Mekkah kembali dengan takbir dan tahlil. Mereka menyaksikan Ka’bah tetap berdiri, dan pasukan penyerang hancur.
Aminah kembali bersama yang lain, didampingi Abdul Muththalib. Di tengah lega dan syukur yang meluap, Abdul Muththalib memandang Aminah lama. Ada keyakinan yang lahir dari pengalaman batin—seolah ia membaca masa depan lewat ketenangan Aminah dan keselamatan kota.
Lalu ia berkata dengan suara yang hangat dan berat maknanya:
Abdul Muththalib: “Selamat untukmu, wahai Aminah. Kemenangan ini, dalam hatiku, seperti pertanda kebaikan bagi janinmu. Sejak engkau mengandung, dunia terasa lebih terang di mataku, dan ketenangan menyelimuti hati.”
Ia menarik napas, lalu menutup dengan harapan yang sangat manusiawi:
Abdul Muththalib: “Semoga Allah memanjangkan umurku agar aku dapat menyaksikan pancaran wajahnya—dan melihat Abdullah hadir kembali, meski hanya dalam raut putranya.”
Lahirlah Sang Cahaya
Aminah menjalani hari dengan lapang dada. Ada ketenangan yang tidak biasa, seolah seluruh rumah memantulkan kenyamanan yang lembut. Menjelang sore, rasa itu tidak mereda; justru semakin jernih. Keindahan tampak lebih dekat, dan Aminah menikmati kelonggaran hati yang lama tidak ia rasakan.
Barakah bekerja dengan cekatan. Ia menyelesaikan tugas-tugas rumah tanpa menunda, lalu beristirahat sejenak dengan dada lega: kelahiran tampaknya kian dekat. Ia tidak berani tidur pulas. Ia menjaga pendengaran, menunggu jika Aminah memanggil tukang bayi.
Malam melewati paruh pertamanya. Aminah sempat tertidur ringan dan bermimpi tentang taman yang lebih sempurna daripada mimpi-mimpi sebelumnya: pohon-pohon menjulang, bunga-bunga mekar, air mengalir, dan burung-burung bernyanyi. Di sela dedaunan, sebuah suara menyapa, lembut namun tegas:
Suara (dalam mimpi): “Bersiaplah, wahai Aminah. Sekarang waktunya.”
Aminah terbangun. Sesaat ia merasa taman itu masih ada—begitu nyata, begitu dekat. Namun saat matanya menyesuaikan, ia melihat kamar, dinding, dan seluruh isi rumah dengan jelas. Ia menarik napas panjang. Lalu ia mendengar suara panggilan lembut dari dalam dirinya, berulang, mendesak tetapi tidak menakutkan. Aminah memanggil Barakah.
Barakah ternyata belum tidur. Ia segera mendekat.
Barakah: “Aku di sini, wahai Tuan Putri.”
Aminah menatapnya, iba.
Aminah: “Engkau belum tidur, Barakah?”
Barakah tersenyum kecil, berusaha membuat malam terasa ringan.
Barakah: “Bagaimana aku bisa tidur, Tuan Putri, ketika malam ini seperti taman yang hidup? Aku takut tidak mendengar panggilanmu.”
Aminah menggeleng pelan.
Aminah: “Jangan larut dalam bayangan, Barakah. Kita di rumah ini.”
Barakah mengangguk cepat, lalu menatap Aminah penuh siaga.
Barakah: “Aku sadar, Tuan Putri. Aku mendengar langkah orang-orang yang bersiap sebelum fajar, suara hewan ternak, dan panggilan kerja dari rumah-rumah sekitar. Aku hanya menunggu perintahmu. Apakah aku harus memanggil tukang bayi?”
Aminah menjawab tenang, seperti orang yang baru saja memahami sesuatu yang besar.
Aminah: “Belum sekarang. Engkau istirahatlah. Tuhan Maha Penyayang.”
Barakah menurut, meski enggan. Setelah ia undur diri, Aminah tidak tidur lagi. Ia bangkit perlahan, seolah dituntun oleh keteguhan yang datang tanpa alasan yang bisa dijelaskan.
Dalam kesunyian, Aminah merasakan seolah ada kehadiran yang mengitari tempat tidurnya—bukan menakutkan, melainkan menenteramkan. Ia seakan mendengar suara perempuan-perempuan yang tidak ia kenal, berbicara dengan gembira:
Suara-suara (seakan dari dekat): “Kabar gembira untukmu, wahai Aminah. Engkau melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan. Lihatlah.”
Aminah menunduk, dan di sana ada seorang bayi—wajahnya bening, tubuhnya kecil, namun memancarkan terang yang halus. Ia melihat bayi itu menempelkan kedua tangannya ke tanah, sementara kepalanya terangkat seolah menatap langit. Aminah bergetar oleh kebahagiaan yang sulit diterjemahkan.
Aminah (berbisik): “Cahaya… ini cahaya.”
Kemudian suara yang sama terdengar lagi, lebih jelas, seperti pesan yang dititipkan:
Suara (lembut): “Berbahagialah, wahai Aminah. Berilah ia nama Ahmad. Ia akan menjadi cahaya yang mengusir gelap. Jagalah ia. Ia akan diuji oleh kaumnya, sebagaimana orang yang membawa pembaruan selalu diuji.”
Aminah menoleh, ingin tahu siapa yang berbicara. Namun cahaya tiba-tiba menguat. Suara-suara itu masih terdengar seperti nyanyian yang jauh, lalu semakin lirih, dan hilang bersamaan dengan datangnya fajar.
Aminah meraih bayinya, menggendongnya erat di dada. Di tengah bahagia, ada luka yang tetap hidup: Abdullah tidak ada di sini untuk menyaksikan kelahiran putranya.
Aminah mengusap wajah bayi itu, air matanya jatuh pelan.
Aminah: “Seandainya ayahmu ada, wahai Ahmad. Seandainya Abdullah melihatmu… dan menyegarkan matanya dengan wajahmu.”
Ia menatap bayi itu lebih lama, lalu menambahkan dengan suara yang lebih rapuh namun tegas:
Aminah: “Engkaulah harapanku, Ahmad. Di dunia ini aku tidak punya siapa-siapa selain engkau. Lekaslah besar… dan isilah ruang yang ditinggalkan ayahmu.”
Di luar kamar, Barakah tidak bisa menahan diri. Ia menari kecil dengan dialek Habsyah-nya, menyenandungkan lagu pendek karena bahagia memuncak—namun air mata menahan kata-kata di tenggorokan. Ia mendekat, suaranya gemetar.
Barakah: “Selamat, wahai Tuan Putri.”
Lalu ia duduk di ruang tengah, menangis bahagia. Setelah menenangkan napas, ia meminta izin untuk bergegas memberi kabar kepada Abdul Muththalib.
Di dekat Ka’bah, Abdul Muththalib belum pulang. Ia duduk menahan gelisah, seolah menunggu sesuatu yang tidak ia bisa sebutkan. Orang-orang yang bertawaf melihatnya dan menegur:
Orang Quraisy: “Masih di sini, wahai Abdul Muththalib? Jangan larut dalam sedih. Engkau bisa jatuh sakit.”
Ucapan itu tidak menghibur—justru mengiris. Abdul Muththalib memejamkan mata, menahan air mata.
Tiba-tiba Barakah datang tergopoh-gopoh. Ia memanggilnya untuk segera menuju rumah Aminah. Abdul Muththalib bangkit seketika, matanya menyala, suaranya bergetar karena harap yang lama tertahan.
Abdul Muththalib: “Kebaikan, wahai Barakah… kebaikan. Bangunkan para perempuan di rumah. Cepat. Dan panggil tukang bayi.”
Barakah menjawab cepat, nyaris seperti orang yang sedang berlari dengan kabar di dada.
Barakah: “Dia sudah melahirkan, tuanku.”
Abdul Muththalib menahan napas.
Abdul Muththalib: “Siapa yang menolongnya?”
Barakah mengangkat wajah, yakin pada apa yang ia rasakan.
Barakah: “Allah yang menolongnya, tuanku. Cahaya… bayi itu bercahaya. Sangat tampan.”
Abdul Muththalib segera berjalan cepat, seperti orang yang muda kembali oleh harapan.
Kegembiraan yang Tak Terbendung
Abdul Muththalib tiba di rumah Abdullah dengan langkah yang nyaris berlari. Nalurinya mendorongnya langsung menuju kamar Aminah. Saat pintu terbuka, matanya seakan disilaukan oleh terang yang lembut—seperti cahaya bulan yang turun dan menetap dalam pangkuan malam. Hatinya bergetar. Ia menahan napas, lalu berbisik penuh takjub:
Abdul Muththalib: “Mahasuci Allah, Pemilik kemuliaan dan kehormatan. Cahaya ini bukan biasa… seakan-akan aku memandang sesuatu yang dimuliakan.”
Ia mendekat, mengulurkan tangan, lalu mengangkat bayi itu perlahan. Dadanya sesak oleh campuran syukur dan kehilangan. Ia mendekap cucunya erat-erat, memejamkan mata, dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Beberapa saat kemudian ia membuka mata, menoleh kepada Aminah, dan berkata lirih—seolah menguji nama yang tiba-tiba mengalir di hatinya:
Abdul Muththalib: “Muhammad… wahai Aminah.”
Aminah menatapnya dengan mata basah, namun suaranya tegas dan tenang—seperti seseorang yang baru selesai menerima amanat.
Aminah: “Ahmad, wahai ayahku. Aku diperintahkan menamainya Ahmad.”
Abdul Muththalib mengangguk pelan. Ia mengecup pipi bayi itu berkali-kali, lalu menjawab dengan suara yang hangat, seolah ingin menautkan dua nama dalam satu makna:
Abdul Muththalib: “Ahmad dan Muhammad—keduanya membawa pujian. Semoga ia terpuji di sisi Allah dan di sisi manusia.”
Ia menimang bayi itu lebih dekat, lalu berdiri. Seperti orang yang tak mau menunda rasa syukurnya, ia membawa cucunya ke Ka’bah. Di sana ia thawaf sambil mendekap bayi itu, berdoa panjang: agar hidup sang anak menjadi kebaikan bagi Makkah, bagi bangsa Arab, dan bagi dunia yang lebih luas daripada yang mereka kenal.
Sesudah selesai, ia kembali ke rumah. Di pangkuannya, bayi itu tampak tenang. Abdul Muththalib mengusap kepala dan tubuh kecil itu dengan doa yang terputus-putus oleh tangis.
Abdul Muththalib: “Muhammad… Muhammad bin Abdullah… semoga semesta menanti kebaikannya.”
Mendengar nama Abdullah disebut, Aminah menunduk. Air mata yang sedari tadi tertahan akhirnya jatuh.
Aminah: “Seandainya Abdullah masih hidup… menyaksikan cahaya ini.”
Abdul Muththalib memalingkan wajahnya, menyembunyikan tangis yang tiba-tiba terasa tajam. Ia keluar menuju Ka’bah, duduk di sana seperti orang yang hatinya dipecah dua: separuh bahagia karena kelahiran, separuh nyeri karena anaknya tak sempat memeluk putranya sendiri.
Orang-orang yang thawaf melihatnya dan memberi selamat, mencoba mengangkatnya dari dukanya.
Orang Quraisy: “Tanggalkan pakaian sedihmu, wahai Abdul Muththalib. Cucumu telah datang.”
Kabar kelahiran putra Abdullah menyebar cepat ke setiap rumah. Warga Makkah berdatangan membawa ucapan selamat. Mereka membicarakan apa yang membuat hati mereka bergetar: bayi itu memancarkan terang, dan Aminah melahirkan dengan tenang—seolah kesakitan tidak diberi ruang pada malam itu.
Fathimah, ibu Abdullah, datang paling awal. Ia membungkuk, mengecup cucunya dengan rindu yang lama dipendam, lalu berdoa agar Allah menjaga anak itu dari keburukan dan hasad manusia. Saudari-saudari Abdullah menyusul dengan hadiah-hadiah ringan, sementara para perempuan rumah tangga dan budak-budak perempuan datang membawa bingkisan yang lebih berat. Lagu-lagu tradisi dinyanyikan pelan, mengisi rumah dengan ritme yang hangat.
Di antara mereka ada Tsuwaibah—perempuan yang kegembiraannya meluap tak terkendali. Ia bernyanyi dan menari, bukan untuk pamer, tetapi seolah merayakan sesuatu yang menyelamatkan hidupnya sendiri.
Tsuwaibah: “Kelahiran paling membahagiakan… Kelahiran paling membahagiakan! Dengan kelahirannya, aku merasakan hidupku kembali.”
Ia mendekap bayi itu sejenak, menangis bahagia. Orang-orang memandangnya heran, sebagian menyindir.
Sebagian perempuan: “Apa yang menimpamu, Tsuwaibah? Cukup sudah—jangan berlebihan.”
Tsuwaibah menoleh, napasnya masih tersengal oleh bahagia, lalu menjawab dengan kata-kata yang keluar dari luka panjang seorang budak.
Tsuwaibah: “Kalian tak tahu rasanya kehilangan kebebasan. Kebebasan lebih mahal daripada emas dan permata. Aku berbahagia karena kelahiran ini menjadi sebab aku merdeka.”
Ia lalu bercerita bagaimana ia berlari membawa kabar kelahiran kepada Abdul ‘Uzza bin Abdul Muththalib. Karena gembira, tuannya memberi hadiah yang tak bisa dibeli: kemerdekaan.
Tsuwaibah: “Ia berkata, ‘Ini kabar paling berharga. Mulai hari ini engkau merdeka.’ Maka bagaimana aku tidak bersyukur pada hari ketika kabar itu datang?”
Sementara itu, Abdul Muththalib di Ka’bah memerintahkan agar perayaan dibuka. Ia ingin kebahagiaan kali ini menjadi kebahagiaan publik—bukan hanya keluarga.
Abdul Muththalib: “Buka jamuan. Sembelih hewan yang gemuk. Biarkan siapa pun makan—tak seorang pun dihalangi.”
Utusan dari tempat dekat dan jauh terus berdatangan membawa ucapan selamat. Namun di balik sorak-sorai, Abdul Muththalib tetap menyimpan pertanyaan yang sunyi: apakah umurnya cukup panjang untuk menyaksikan cucunya tumbuh?
Dalam hati ia berbisik, nyaris seperti doa yang malu-malu diucapkan.
Abdul Muththalib (dalam hati): “Aku kakekmu, wahai Muhammad. Akankah aku sempat melihat masa depanmu… sebelum waktuku habis?”
Ibu Radha’
Suatu pagi Aminah terbangun. Ia membuka mata dan mendapati putranya tersenyum—wajah kecil itu bening, tenang, seakan tak mengenal duka. Aminah membalas senyum itu, lalu rasa bahagia menyusup pelan. Namun kebahagiaan itu tidak pernah benar-benar selesai; ia selalu punya pintu menuju ingatan.
Nama Abdullah muncul seperti bayang-bayang yang menempel pada cahaya.
Aminah terdiam. Dalam kepalanya berputar kembali segalanya: nazar yang nyaris menelan suaminya, tebusan yang mengubah manusia menjadi undian, perjalanan dagang yang memisahkan, dan kabar kematian yang menutup pintu pertemuan untuk selamanya.
Ia bertanya kepada dirinya sendiri, dengan suara yang hanya didengar hatinya:
Aminah (dalam hati): “Apakah Abdullah hanya diberi waktu untuk menitipkan anak ini, lalu pergi? Mengapa ia diselamatkan dari tebusan—tetapi akhirnya diambil juga?”
Air mata Aminah jatuh pelan. Ia membayangkan Abdullah dalam tanah yang teduh: di bawah pohon kurma dan anggur yang merunduk, seakan alam sendiri memberi naungan bagi tubuh yang pergi terlalu cepat. Ia membayangkan para malaikat mengitari makam itu—bukan untuk menghibur Aminah, tetapi untuk menguatkan keyakinannya bahwa Abdullah pergi dalam keadaan bersih.
Namun keyakinan tidak selalu membunuh pedih. Kadang ia justru membuat pedih terasa lebih nyata.
Aminah menunduk, menatap putranya.
Aminah (dalam hati): “Apakah semua ini digariskan agar anak ini tumbuh sendiri—tanpa sandaran ayah, tanpa penopang harta? Agar ia berjalan hanya dengan pertolongan Tuhan?”
Ia mengusap air matanya, lalu meraih Muhammad, bersiap menyusuinya. Namun ketika bayi itu mendekat ke dadanya, Aminah tersentak: air susunya mengering, padahal beberapa hari sebelumnya masih melimpah.
Ia menahan napas, heran dan takut sekaligus.
Aminah: “Ke mana perginya air susu itu? Aku mengandung tanpa payah, melahirkan tanpa sakit… dan kini ini terjadi. Apa yang harus kulakukan?”
Ia memanggil Barakah. Sang pembantu datang dengan wajah yang berusaha tegar, meski matanya menyimpan genangan.
Aminah bertanya tentang perempuan-perempuan pedalaman yang biasa datang mencari bayi susuan—para ibu susu yang membawa bayi-bayi bangsawan Quraisy ke kampung mereka hingga masa sapih.
Barakah menggeleng.
Barakah: “Mereka belum datang, wahai tuan putriku.”
Aminah memandangnya lebih lama dari biasanya. Ia menangkap sesuatu yang lain: kesedihan yang belum selesai.
Aminah: “Mengapa engkau muram, wahai Barakah? Bukankah kita sepakat menahan duka—demi menjaga Muhammad?”
Barakah menunduk, lalu menjawab dengan suara yang jujur, seperti orang yang menyerahkan isi dada tanpa hiasan kata.
Barakah: “Seandainya ada susu di dadaku, aku akan menyusuinya. Aku tak ingin ada perempuan lain memeluknya dan memberi makan kepadanya.”
Ucapannya mengguncang Aminah. Ia melihat, kesetiaan Barakah bukan sekadar tugas budak—melainkan ikatan jiwa yang tumbuh tanpa diminta.
Aminah menghela napas, melembutkan suaranya.
Aminah: “Semoga Allah memuliakanmu, wahai Barakah.”
Namun Barakah menggeleng keras, seperti seseorang yang sudah mengunci pilihan hidupnya.
Barakah: “Tidak, tuan putriku. Sejak melihat tuan kecilku, aku telah meniatkan hidupku untuknya. Aku tidak ingin menjadi milik siapa pun selain amanat ini.”
Belum sempat Aminah menjawab, Tsuwaibah masuk. Ia mendekat ke pembaringan bayi, mengecup keningnya, lalu menatap Aminah dengan mata yang menyala oleh harap.
Tsuwaibah: “Apakah engkau mengizinkanku mendapat kehormatan yang akan kupegang sepanjang hidupku?”
Aminah: “Kehormatan apa, wahai Tsuwaibah?”
Tsuwaibah: “Hatiku mendorongku kemari. Aku ingin menyusui Muhammad. Jika engkau mengizinkan, aku akan bahagia sepanjang umurku.”
Aminah menatap dada Tsuwaibah—penuh susu, siap memberi hidup.
Ia tersenyum kecil, getir sekaligus lega.
Aminah: “Aku memang hendak memanggilmu. Air susuku mengering, dan aku tak mengerti sebabnya.”
Tsuwaibah segera menyusui Muhammad. Bayi itu tenang. Dan Tsuwaibah seolah menemukan tempatnya sendiri di dunia.
Tsuwaibah: “Jika engkau berkenan, izinkan aku menyusuinya lebih lama. Biarkan aku menjadi ibu susunya.”
Barakah menyela, tegas namun tetap sopan.
Barakah: “Para perempuan Bani Sa‘ad akan datang. Biasanya mereka membawa bayi ke pedalaman sampai masa sapih.”
Tsuwaibah memandang Barakah, tidak marah—hanya keras kepala karena cinta.
Tsuwaibah: “Mereka datang untuk upah, Barakah. Aku datang karena hati. Susuku bertambah sejak disentuh mulut Muhammad. Aku tak kuasa berpisah dengannya.”
Belum selesai perdebatan itu, seperti dipanggil oleh takdir, rombongan perempuan Bani Sa‘ad benar-benar memasuki Makkah. Mereka datang dari pedalaman dengan satu tujuan: memperoleh bayi susuan dari keluarga Quraisy—bayi bangsawan kaya yang kelak memberi mereka upah tinggi dan menyelamatkan keluarga dari musim kering.
Di antara rombongan itu ada Halimah as-Sa‘diyyah. Ia datang dengan keledai betina yang kurus dan lamban, menggendong anaknya yang lemah karena lapar. Suaminya mengikuti di belakang dengan unta tua yang hampir rubuh. Mereka tertinggal di akhir barisan, menjadi bahan ejekan.
Perempuan-perempuan Sa‘ad: “Mengapa engkau ikut, Halimah? Dengan keadaanmu begitu, siapa yang mau menitipkan bayi kepadamu?”
Kafilah tertawa. Halimah tetap tenang. Ia menjawab tanpa terpancing.
Halimah: “Kalian akan melihat. Siapa yang tahu kehendak Tuhan?”
Setibanya di Makkah, para perempuan pedalaman itu memperindah diri, lalu berpencar mendatangi rumah-rumah bangsawan. Mereka mencari bayi—bukan sekadar bayi, melainkan bayi yang menjanjikan.
Saat mereka melintas di depan rumah Abdullah, Barakah sudah menunggu di depan, sementara Aminah mengamati dari dalam. Anak-anak di jalan berteriak memberi petunjuk.
Anak-anak: “Bayi baru lahir! Bayi baru lahir!”
Mereka menoleh. Mereka mendengar seruan Barakah.
Barakah: “Bayi keturunan mulia dan bangsawan, wahai para ibu susu!”
Beberapa perempuan masuk. Mereka tertegun melihat Aminah, lalu terpaku saat memandang bayi itu—seakan ada cahaya yang membuat mata mereka segan berkedip. Mereka saling berebut ingin mengambilnya.
Namun para perempuan itu bukan hanya pemburu keindahan; mereka pemburu kepastian.
Salah satu bertanya, hati-hati namun tajam:
Ibu susu: “Di mana ayahnya, wahai Aminah?”
Aminah menunduk. Air mata menggenang tanpa diminta.
Aminah: “Ia yatim. Ayahnya wafat saat ia masih janin.”
Mereka terdiam sejenak. Lalu satu pertanyaan lain muncul—lebih telanjang, lebih menentukan:
Ibu susu: “Apakah ayahnya meninggalkan warisan besar?”
Aminah mengusap pipinya, lalu menjawab jujur, tanpa menambah dan tanpa mengurangi.
Aminah: “Ia hanya meninggalkan sedikit unta dan kambing, seorang budak—Barakah—dan rumah ini.”
Hening berubah menjadi dingin. Harapan yang semula berkilat padam tiba-tiba. Para perempuan itu saling pandang, lalu mundur satu demi satu.
Mereka keluar dengan gumam yang tidak sepenuhnya disembunyikan.
Salah satu ibu susu (berbisik sinis): “Dengan apa kita dibayar? Dengan beberapa kambing dan rumah sempit?”
Mereka pergi, meninggalkan Aminah dengan tangis yang kembali jatuh. Barakah menunduk sedih. Namun Tsuwaibah justru menahan senyum—ia merasa peluangnya terbuka.
Di luar, rombongan perempuan itu menertawakan Halimah, seolah melemparkan sisa yang tidak mereka inginkan.
Perempuan-perempuan Sa‘ad: “Ambillah, Halimah! Bayi yatim dan fakir itu cocok untukmu!”
Halimah menatap ke arah rumah itu. Ada iba yang menahan langkahnya, seolah hatinya ingin berbalik. Namun ejekan yang menusuk membuatnya ragu: antara belas kasihan dan kebutuhan hidup.
Ia menggigit bibir, menahan malu, lalu melangkah berat menyusul rombongan—menjauh dari rumah bayi yang baru saja ditolak.
Halimah as-Sa’diyah
Para ibu susu menyebar ke rumah-rumah bangsawan Makkah. Di depan gerbang rumah megah, mereka mempromosikan diri: senyum, gaya bicara, dan dandanan disusun rapi untuk memikat hati para ibu.
Di salah satu rumah, seorang ibu memilih seorang perempuan yang paling meyakinkan. Anak diserahkan dengan uang, hadiah, dan pesan yang dibisikkan berulang-ulang—seolah kasih sayang dapat dititipkan bersama upah.
Perempuan-perempuan lain pun mendapat bagian. Satu per satu mereka keluar dari rumah-rumah bangsawan dengan wajah berbinar: masing-masing membawa bayi susuan, disertai janji upah besar dan makanan yang cukup.
Hanya Halimah yang tetap sendiri.
Ia berdiri agak jauh, menenangkan bayinya yang menangis karena lapar. Pakaian Halimah lusuh, tubuhnya dipenuhi debu perjalanan, dan rautnya tampak letih—seolah kemiskinan menempel pada wajahnya sebelum sempat ia bicara.
Ketika semua perempuan bersiap pulang ke luar kota, Halimah ikut berjalan di belakang. Kakinya berat. Ia pulang tanpa bayi susuan, tanpa perjanjian, tanpa kepastian.
Di tempat perbekalan, Halimah berhenti. Ia menoleh ke arah Makkah—pandangan matanya tersangkut pada rumah Abdullah, rumah yang tadi ia lewati… rumah bayi yatim yang ditolak perempuan-perempuan lain.
Di dekat sana, para suami menyambut istri-istri mereka dengan sorak gembira. Tangan-tangan menyalami, mulut-mulut mengucapkan selamat, seolah seorang bayi bangsawan adalah tiket keluar dari musim kering.
Halimah menelan ludah. Dadanya sesak. Ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan: kerinduan yang mendadak pada bayi yang bahkan bukan miliknya.
Kakinya bergerak satu langkah ke arah Makkah, lalu berhenti lagi.
Halimah (dalam hati): “Apa yang kau bisikkan, wahai hatiku? Apa yang bisa kudapat dari bayi yatim dan fakir itu? Ia tidak punya ayah kaya. Ibunya pun tak berharta. Aku miskin—dia pun miskin. Apa aku hanya menambah beban hidupnya dengan kemelaratan hidupku?”
Halimah menatap keledainya yang kurus, lalu menatap kantong susu unta yang kosong. Ia tahu: di kampung, susu langka; hujan jarang; tanah keras. Ia bahkan takut pada ejekan ketika pulang tanpa hasil.
Namun bisikan itu kembali, lebih keras dari rasa malu.
Halimah (dalam hati): “Kembalilah. Ambil dia. Engkau tidak tahu di mana keberuntungan disembunyikan.”
Halimah menghela napas, seolah memarahi dirinya sendiri.
Halimah (dalam hati): “Mengapa justru bayi itu yang memanggilku? Aku tidak tergoda bayi-bayi bangsawan berselimut sutra. Mengapa aku terpikat pada bayi yatim itu—dan pada ibunya yang menahan tangis?”
Kafilah sudah bergerak. Yang tersisa hanya Halimah, suaminya (Harits), keledai kurus, dan unta tua.
Halimah kembali ke arah Harits dengan tangan kosong. Harits memandangnya, dan kekhawatirannya runtuh menjadi getir.
Harits: “Aku sudah menduga, Halimah. Orang miskin hampir tak punya tempat dalam dunia ini. Kita datang menahan berat perjalanan—lalu pulang tanpa apa-apa. Yang lain membawa bayi bangsawan, kita membawa lapar.”
Halimah diam, menahan pedih. Bayi mereka merengek. Harits melanjutkan, suaranya keras karena kecewa, bukan karena benci.
Harits: “Dunia ini menipu. Seandainya kau menampilkan diri seperti perempuan lain—lebih ‘meyakinkan’, lebih pandai berkata-kata—mungkin kita tidak dipulangkan kemiskinan seperti ini.”
Halimah menatap suaminya, lalu menjawab pelan namun teguh.
Halimah: “Apa hidup harus dibeli dengan dusta, Harits? Aku tidak mampu memakai topeng kepalsuan. Lidahku kaku saat harus berlebihan memuji diri. Aku datang membawa niat menjadi ibu susu, bukan menjadi pedagang kata-kata.”
Harits menghela napas panjang. Ia memandang kafilah yang makin jauh, lalu kembali pada wajah Halimah.
Harits: “Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pulang ke kampung dan menanggung ejekan? Anak kita sendiri menangis kelaparan, Halimah.”
Halimah menunduk sejenak. Lalu seolah membuka pintu yang sejak tadi ia tahan rapat.
Halimah: “Ada satu bayi yang membuatku tidak perlu berdusta, Harits.”
Harits menatap tajam, seakan menangkap peluang terakhir.
Harits: “Siapa?”
Halimah: “Bayi Abdullah… tetapi ia yatim dan miskin.”
Kalimat itu membuat Harits terdiam. Di matanya, “yatim dan miskin” berarti “tanpa upah” dan “tanpa jaminan”. Namun di balik itu, ia melihat sesuatu yang lain: mengapa hati istrinya justru terpaut pada bayi yang ditolak semua orang?
Halimah segera melanjutkan, suaranya menjadi lebih hidup—seolah keberanian yang semula gemetar kini menemukan pijakan.
Halimah: “Semua perempuan berpaling ketika tahu dia yatim. Tapi hatiku tidak bisa. Ada sesuatu yang menahanku dari bayi-bayi lain dan mendorongku ke rumah itu. Wajahnya… seperti bulan. Ibunya pun demikian—menahan air mata, menahan runtuh. Aku merasa… bayi itu membawa kebaikan.”
Harits memandang anak mereka yang masih menangis, memandang keledai kurus, memandang unta tua. Ia menghitung kenyataan—lalu menimbangnya dengan keyakinan.
Akhirnya ia bicara, lebih lembut.
Harits: “Kalau begitu, jujurlah: apakah cintamu pada bayi itu tulus? Dan apakah ibunya mau menyerahkan bayinya pada orang semiskin kita?”
Halimah menjawab cepat, seolah takut keraguannya keburu dipotong.
Halimah: “Aku tidak bisa menjelaskan, Harits. Tapi aku tahu: aku ingin merawatnya bukan karena upah, melainkan karena hati. Dan rezeki… bukan milik manusia.”
Harits memejamkan mata sejenak. Lalu ia mengangguk pelan, seperti seseorang yang akhirnya menyerahkan takutnya kepada Tuhan.
Harits: “Allah memberi rezeki kepada siapa pun yang Dia kehendaki. Mungkin bayi itu ditolak orang lain agar menjadi bagian kita. Jika Allah memalingkannya dari mereka tetapi tidak dari kita, berarti ada hikmah. Pergilah, Halimah.”
Halimah menatapnya—tidak percaya.
Halimah: “Engkau rela?”
Harits mengangguk, sambil menenangkan anak mereka yang menangis.
Harits: “Pergilah kepada Muhammad. Kembalilah bersamanya. Semoga Allah melapangkan hati ibunya. Jika ada keberuntungan yang halal, ia adalah keberkahan. Dan keberkahan itulah keberuntungan kita.”
Halimah menarik napas panjang. Ia menoleh sekali lagi ke arah Makkah—kali ini bukan dengan ragu, melainkan dengan tekad. Langkahnya bergerak kembali menuju rumah bayi yatim yang tadi ditinggalkan semua orang.
Berpisah dengan Sang Buah Hati
Halimah meninggalkan bayinya bersama Harits di luar Makkah, lalu bergegas kembali—langkahnya cepat, napasnya pendek, seolah takut terlambat satu detik saja. Sesampainya di rumah Abdullah, ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar.
Dari balik pintu terdengar suara yang tegas.
Suara di dalam: “Siapa?”
Halimah menjawab dengan rindu yang pecah di ujung kata.
Halimah: “Halimah as-Sa’diyyah, wahai tuan putri. Aku datang menjemput si kecil.”
Jawaban yang diterimanya tajam, bercampur luka.
Barakah (dari dalam): “Banyak yang sudah menolaknya, wahai perempuan, karena dia yatim dan fakir. Kami tidak akan menyerahkan anak itu kepada orang-orang yang datang hanya demi harta.”
Halimah tersentak. Jantungnya berdegup lebih keras, bukan karena tersinggung, melainkan karena takut kesempatan terakhir ini hilang. Ia menahan suara, memilih lembut agar pintu tetap terbuka.
Halimah: “Aku pun miskin, seperti dia. Aku tidak datang membawa tipu daya. Aku hanya berharap Allah menurunkan kebaikan-Nya melalui bayi ini. Bukalah pintu—jangan halangi aku dari rezeki yang Tuhan titipkan.”
Di dalam rumah, Aminah duduk dengan hati yang belum pulih. Penolakan para perempuan penyusu terasa seperti penolakan terhadap hidupnya sendiri: suaminya telah pergi, warisan tak banyak, dan kini anaknya pun seperti tak ada yang bersedia memeluknya.
Mendengar percakapan Halimah dan Barakah, Aminah memerintahkan agar pintu dibuka.
Halimah masuk. Debu masih melekat di pakaiannya, tetapi matanya menyala—penuh tekad. Ia duduk di hadapan Aminah dan berbicara tanpa berputar.
Halimah: “Wahai tuan putri, izinkan aku menyusui putramu. Hatiku tertaut kepadanya sejak pertama melihatnya. Aku tidak menjanjikan kemewahan, tetapi aku menjanjikan kasih sayang. Aku akan meletakkan dia di tempat paling terhormat di dalam hatiku.”
Tsuwaibah—yang sejak awal membantu menyusui Muhammad—menyela dengan nada yang berusaha tenang, namun menyimpan kekhawatiran.
Tsuwaibah: “Tapi engkau dulu ikut berpaling. Engkau pun mengincar bayi bangsawan, seperti yang lain.”
Halimah menatap Tsuwaibah tanpa marah.
Halimah: “Benar, aku datang mencari jalan keluar dari lapar. Tapi ketika aku melihatnya, aku tahu: rezeki bukan hanya soal upah. Aku kembali bukan karena dia ‘menguntungkan’, melainkan karena aku tidak sanggup meninggalkannya.”
Tsuwaibah menilai Halimah dari kenyataan yang paling keras: dada yang tampak kering, tubuh yang kurus, dan musim paceklik yang belum selesai.
Tsuwaibah: “Kalau begitu, cobalah susui dia. Tidak semua bayi menerima susu dari siapa pun.”
Ucapan itu membuat Halimah kaku sesaat—karena ia tahu: air susunya hampir tak ada. Namun ada kekuatan yang mendorongnya maju. Ia meraih Muhammad perlahan, seolah meminta izin pada Aminah lewat gerak tangannya, lalu mendekapkan bayi itu ke dadanya dengan rasa takut yang ditahan rapat.
Detik berikutnya mengubah semuanya.
Muhammad menempel, menyusu tenang. Halimah terkejut—dadanya terasa penuh, hangat, dan air mata mengalir tanpa diminta. Ia menatap Aminah, suaranya bergetar oleh syukur.
Halimah: “Lihatlah, wahai tuan putri. Dia menerimaku… dan susu ini mengalir. Demi Allah, ini bukan kekuatanku.”
Halimah menoleh pada Tsuwaibah, bukan untuk menang, melainkan untuk menegaskan keajaiban yang sama-sama mereka lihat.
Halimah: “Jangan heran pada rahmat Tuhan. Dia memberi setelah manusia putus asa.”
Halimah kembali menghadap Aminah, kini dengan permohonan yang lebih sederhana—lebih jujur.
Halimah: “Jika tuan putri berkenan, izinkan aku membawa Muhammad kepada suamiku di luar Makkah. Kami hendak menyusul kafilah pulang ke Bani Sa’ad.”
Aminah memandangi putranya. Air mata yang ia tahan sejak lama naik lagi—bukan karena ia ragu, melainkan karena ia harus merelakan.
Ia masuk ke kamar, kembali membawa kain kecil. Tangannya membalut tubuh Muhammad dengan hati-hati, lalu ia memeluk bayi itu erat—pelukan seorang ibu yang baru saja kehilangan suami, dan kini harus melepas anaknya demi hidup yang lebih kuat.
Aminah mencium pipi Muhammad, lalu menyerahkannya kepada Halimah.
Halimah keluar dengan langkah cepat, Barakah mengiringi hingga jauh. Dan ketika pintu tertutup, Aminah duduk kembali—sepi mendadak menampar dinding rumah.
Aminah (lirih): “Ini perpisahan yang lain, wahai Muhammad. Ayahmu pergi setelah pertemuan yang singkat, dan kini engkau pun pergi setelah singkat pula. Akankah aku sempat melihatmu kembali… atau tugasku segera selesai?”
Di luar Makkah, Harits masih berdiri menunggu, menggendong anak mereka yang lemah. Halimah datang dengan Muhammad di pelukannya. Harits terpaku—bukan karena kain yang membalut, tetapi karena ketenangan yang memancar dari bayi itu.
Harits: “Masya Allah… ini berkah, Halimah.”
Halimah menjawab cepat, suaranya penuh keyakinan baru.
Halimah: “Dan susu itu kembali mengalir, Harits. Bawakan anak kita—biar dia merasakan.”
Halimah menyusui anaknya sendiri. Harits tercengang melihat susu yang dulu kering kini mengalir deras.
Harits: “Apa engkau makan sesuatu?”
Halimah: “Demi Allah, tidak. Muhammad mendekat—lalu Allah yang mencukupkan.”
Harits memandang unta mereka. Ambingnya tampak penuh, seolah tubuh tua itu tiba-tiba mengingat cara memberi. Ia memerah—susu tumpah deras.
Harits (terperanjat): “Melimpah, Halimah… melimpah!”
Mereka pun bergegas menyusul kafilah. Keledai Halimah yang dulu tertatih kini berlari cepat; unta tua yang dulu lamban kini kuat. Mereka menyalip dan mendahului rombongan.
Orang-orang kafilah berteriak dari jauh, heran melihat pemandangan yang tak masuk akal bagi mereka.
Orang kafilah: “Itu Halimah? Itu keledainya? Itu untanya? Bagaimana bisa?”
Halimah menjawab tanpa sombong—lebih seperti orang yang sedang bersaksi.
Halimah: “Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki. Kami hanya menerima.”
Setiba di kampung Bani Sa’ad, perubahan nyata: rumah yang semula sesak oleh kelaparan menjadi lapang. Anak-anak kenyang. Ternak Halimah pulang dengan perut penuh dan susu melimpah. Tetangga heran, iri, lalu mencoba meniru—menggembalakan ternak di tempat yang sama—namun hasilnya tak berubah.
Ketika mereka mendesak bertanya, Halimah hanya tersenyum.
Halimah: “Berkah itu dari Allah. Dia membagi rezeki sesuai kehendak-Nya.”
Tahun berjalan. Muhammad tumbuh cepat—lebih kuat dari anak seusianya. Padang pasir membentuknya: tegar, jujur, berani, dan peka pada sekitar.
Di Makkah, Aminah menunggu dalam rindu yang panjang. Abdul Muththalib sering datang membawa kabar dari Bani Sa’ad—tentang kesehatan Muhammad dan tanda-tanda kebaikan yang mengiringinya.
Dua tahun berlalu. Para ibu susu kembali ke Makkah mengantar anak-anak susuan mereka. Kali ini Halimah bukan lagi yang diejek. Kendaraannya paling cepat, wajahnya lebih tenang, dan Muhammad di pelukannya menjadi pusat pandangan.
Setibanya di Makkah, rombongan berpisah. Masing-masing menuju rumah keluarga bayi yang mereka asuh—membawa anak, menagih upah, dan menutup satu bab perjalanan.
Dan di hadapan Aminah, “perpisahan kedua” segera menemukan pintunya sendiri: pertemuan yang dinanti… sekaligus ujian untuk melepas kembali.
Pertemuan Sekilas dengan Buah Hati
Kota Makkah mulai ramai oleh kabar kedatangan rombongan ibu-ibu penyusu dari Bani Sa’ad. Sejak pagi, para perempuan bersiap menyambut anak-anak yang dua tahun lamanya berada di padang pasir. Di kepala mereka, bayangan bayi yang dulu kecil dan rapuh bercampur dengan harapan: anak itu kini sudah tinggi, tegap, dan lincah.
Aminah bangkit cepat. Ia berdiri di balik pintu, mendengarkan hiruk-pikuk dari kejauhan dengan dada yang penuh rasa. Kabar kafilah selalu mengingatkannya pada hari paling pahit: saat rombongan Quraisy pulang tanpa Abdullah. Karena itu, kegembiraannya bercampur takut—takut ada kabar buruk yang kembali menunggu di ujung jalan.
Barakah berlari lebih dulu. Ia ingin melihat tuan kecilnya sebelum orang lain sempat memeluknya. Di ujung jalan ia melihat para perempuan Bani Sa’ad berdatangan, masing-masing membawa anak susuan menuju rumah keluarganya.
Pandangan Barakah tertahan pada seorang perempuan yang ia kenali dari raut wajahnya—Halimah as-Sa’diyyah—namun kini berbeda: wajahnya berseri, tubuhnya tampak kuat, seolah hidup baru mengalir dalam setiap geraknya. Di pelukannya ada seorang anak laki-laki yang tampan, matanya tajam, senyumnya tenang.
Barakah menahan napas.
“Benarkah itu Halimah?” batinnya. “Dan benarkah itu tuan kecilku?”
Ketika Halimah melangkah menuju rumah Aminah, Barakah yakin. Ia berlari mendahului, masuk ke rumah, lalu berseru gembira.
Barakah: “Tuan putriku, Muhammad sudah datang! Wajahnya berseri, tubuhnya tegap, senyumnya meneduhkan. Kabar gembira, wahai tuan putriku!”
Namun kegembiraan Barakah segera berubah menjadi kecemasan. Ia mendekat dan berbisik dengan nada takut.
Barakah: “Doakan dia selalu dilindungi. Banyak mata iri, banyak hati dengki. Jagalah dia dari hasad manusia.”
(Adegan ini saya rapikan: unsur “jimat” dan “dukun” saya ubah menjadi bentuk kewaspadaan dan doa, agar dialog lebih wajar, lebih halus, dan konsisten dengan suasana religius yang kuat pada bab-bab sebelumnya.)
Belum selesai Barakah berbicara, Halimah tiba membawa Muhammad. Ia menunjuk sekeliling rumah, menuntun anak itu dengan suara lembut.
Halimah (kepada Muhammad): “Ini rumah tempat engkau dilahirkan, wahai Muhammad. Engkau sekarang di Makkah, dekat Baitullah.”
Aminah menyambut mereka dengan langkah tergesa. Ia meraih Muhammad, mengangkatnya ke dada, lalu menciumi pipinya berkali-kali. Ketika bibirnya menyentuh kulit anak itu, seolah dua tahun rindu runtuh sekaligus.
Aminah (terisak): “Muhammad… di sini engkau, wahai Muhammad.”
Halimah tersenyum, memperkenalkan dengan tenang.
Halimah: “Ini ibumu yang melahirkanmu. Aku hanya ibumu yang menyusuimu.”
Muhammad melekat di dada Aminah seperti menemukan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa nama. Ia menatap wajah Aminah, lalu bertanya lirih.
Muhammad: “Di mana aku sekarang, Ibu?”
Aminah: “Di rumahmu, Nak.”
Sesaat kemudian Muhammad bertanya lagi, polos dan jernih, pertanyaan yang tidak siap didengar hati seorang ibu.
Muhammad: “Kalau begitu… di mana ayahku?”
Aminah tersedu. Barakah memalingkan wajah, menyembunyikan tangisnya. Halimah, dengan hati-hati, menata kata agar tidak melukai.
Halimah: “Ayah susuanmu adalah Harits, suamiku. Adapun ayah kandungmu adalah Abdullah bin Abdul Muththalib.”
Muhammad menoleh ke sekeliling rumah, heran.
Muhammad: “Mengapa aku tidak melihatnya? Aku ingin bertemu.”
Halimah menahan napas.
Halimah: “Ayahmu sudah pergi ke tempat yang jauh, wahai Muhammad.”
Muhammad: “Kapan dia kembali?”
Halimah: “Semua kembali kepada kehendak Allah. Ada perkara yang waktunya tidak kita pegang.”
Muhammad diam sejenak, lalu rasa ingin tahunya bergerak seperti angin padang pasir. Ia berjalan memeriksa sudut-sudut rumah, menatap benda-benda yang asing baginya. Kemudian ia teringat sesuatu yang sering ia dengar tentang Makkah.
Muhammad: “Di mana Ka’bah? Bukankah orang yang datang ke Makkah biasa bertawaf dahulu?”
Barakah, yang masih mengusap sisa air mata, segera mendekat.
Barakah: “Aku akan menemanimu, tuan kecilku. Mari.”
Pada saat itulah pintu terbuka. Abdul Muththalib masuk dengan napas berat, seolah ia berlari dari rindu.
Abdul Muththalib: “Di mana Muhammad, wahai Aminah? Di mana putra Abdullah?”
Matanya lebih cepat menemukan Muhammad. Wajahnya seketika berubah: kagum, haru, dan sejenis keyakinan yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa biasa.
Abdul Muththalib: “Masya Allah…”
Ia mengangkat Muhammad, memeluknya erat—bukan hanya memeluk cucu, tetapi seakan memeluk kembali bayangan Abdullah yang telah hilang. Lalu, tanpa menunggu lama, ia membawa Muhammad menuju Ka’bah. Ia mengajak cucunya bertawaf, berdoa, dan mensyukuri pertemuan yang lama tertunda.
Orang-orang di sekeliling memandangi dengan heran: anak kecil itu tampak lebih tegap dari umurnya, lebih tenang dari kebanyakan anak.
Di rumah, Aminah menerima ucapan selamat dari para perempuan. Barakah bolak-balik menyuguhi tamu, menyambut mereka dengan mata yang masih basah namun bahagia.
Halimah duduk di tengah para tamu, bercerita tentang kehidupan Bani Sa’ad: tentang padang pasir yang keras, tentang anak-anak yang tumbuh mandiri, tentang perempuan kampung yang bekerja tanpa banyak keluh. Sebagian tamu tersenyum dan tertawa kecil mendengar kelugasan Halimah—bukan mengejek, melainkan terhibur oleh kejujurannya yang polos dan terang.
Malam turun. Tamu pulang satu per satu. Muhammad telah tidur lebih dulu. Aminah berbaring di sampingnya, memandangi wajah yang ia rindukan dua tahun. Tangannya mengusap kepala dan tubuh anak itu pelan, seakan memastikan ia benar-benar kembali.
Barakah terjaga. Kebahagiaan mengusir kantuk dari matanya.
Saat fajar menyingsing, Halimah duduk di ruang tengah. Ada gelisah yang samar di wajahnya—bukan gelisah takut, melainkan gelisah rindu pada kampung, suami, dan anak-anaknya. Ketika Aminah keluar, Halimah segera membuka maksudnya.
Halimah: “Tuan putri… izinkan aku pulang.”
Aminah menahan rasa kaget.
Aminah: “Mengapa terburu-buru? Baru semalam engkau di sini.”
Halimah menunduk sopan, lalu menjelaskan pelan.
Halimah: “Di kampung, banyak yang menunggu. Tugas perempuan desa berat. Jika aku lama, rumah menjadi pincang. Dan… aku tidak sanggup berpisah dari Muhammad.”
Aminah menatap Halimah—paham ke mana arah kata itu akan berujung. Ia bertanya, meski jawabannya sudah ia duga.
Aminah: “Jadi… engkau ingin membawa Muhammad kembali?”
Halimah mengangguk.
Halimah: “Muhammad telah menjadi napas hidup kami. Sejak ia bersama kami, keadaan berubah. Aku tidak meminta karena tamak, tuan putri. Aku memohon karena cinta.”
Aminah diam sejenak. Ia menimbang antara rindu seorang ibu dan keyakinan bahwa padang pasir telah membuat Muhammad kuat. Akhirnya, ia mengalah pada kasih sayang yang paling pahit: merelakan.
Aminah: “Aku izinkan… dengan satu syarat: bawalah ia mengunjungi kami dari waktu ke waktu. Jangan lama-lama menghilang, wahai Halimah. Rinduku belum terbayar.”
Halimah menjawab cepat—seakan takut izin itu berubah.
Halimah: “Kebaikan terbaik adalah yang tidak ditunda, tuan putri.”
Aminah memeluk Muhammad. Ia mencium pipi kanan, pipi kiri, lalu menciumnya lagi. Muhammad membalas dengan dua kecupan kecil, lalu melambaikan tangan saat Halimah menggendongnya pergi.
Muhammad (lirih): “Sampai jumpa, Ibu… sampai jumpa.”
Aminah berdiri di ambang pintu sampai langkah mereka hilang. Pada hari itu, ia belajar lagi: pertemuan pun dapat menjadi bentuk lain dari perpisahan.
Kembali kepada Pelukan Ibunda
Halimah kembali ke perkampungan Bani Sa’ad sambil menggendong Muhammad. Kedatangannya disambut seperti orang pulang membawa kemenangan. Penduduk kampung berbondong-bondong menemuinya—bukan karena hadiah, melainkan karena kehadiran Muhammad yang mereka yakini membawa kebaikan. Anak-anak berlarian menyambut, para ibu tersenyum lega, dan para lelaki menatap dengan harap: semoga anak itu tetap tinggal, semoga berkah itu tidak pergi.
Muhammad segera berbaur. Ia berlari di padang terbuka, bermain di udara yang luas, disukai teman-temannya, dan dipeluk hangat oleh keluarga Halimah. Syaima, putri Halimah, ditugasi menjaga Muhammad seperti menjaga adik kandung sendiri—setiap langkahnya diawasi, setiap pergaulannya diperhatikan.
Di Makkah, Aminah menahan rindu. Ia merasa tenang karena Muhammad bersama Halimah, tetapi ia tetap “mengirimkan hati” menemaninya: memikirkan tidurnya, makanannya, dan bahaya yang mungkin tidak terlihat.
Hari-hari berjalan biasa sampai suatu siang Syaima membawa Muhammad bermain agak jauh dari perkampungan. Dari kejauhan ia melihat sekelompok orang berkerumun di sekitar Muhammad. Tatapan mereka tidak seperti tatapan orang yang sekadar ingin menyapa anak kecil. Ada sikap mengintai—seolah menimbang kesempatan. Syaima merinding. Ia segera menarik langkah pulang dan berlari menemui ibunya.
Syaima: “Ibu, tadi ada orang-orang mengerumuni Muhammad. Tatapan mereka aneh… seperti orang mengincar sesuatu.”
Halimah terdiam. Dadanya sesak. Ia membayangkan dua kemungkinan: mereka bisa saja perampas yang menculik anak-anak untuk dijual kepada para pedagang budak; atau musuh kabilah yang iri melihat Bani Sa’ad seolah “beruntung terus” sejak Muhammad tinggal bersama mereka.
Malam itu Halimah duduk bersama suaminya, al-Harits. Mereka membicarakan apa yang harus dilakukan. Al-Harits terpancing amarah, suaranya meninggi.
Al-Harits: “Jika mereka kembali, aku akan menghadapi mereka dengan pedang. Aku tidak akan membiarkan siapa pun mendekati anak itu.”
Halimah menenangkannya, suaranya tegas namun tidak meledak.
Halimah: “Bukan itu jalan yang paling selamat, wahai al-Harits. Kita harus mengembalikan Muhammad kepada keluarganya.”
Al-Harits tersentak. Ia menatap Halimah seolah tidak percaya.
Al-Harits: “Mengembalikan? Lalu apa kata orang Makkah tentang kita? Mereka akan berkata kita tak mampu menjaga amanat. Kita akan dipermalukan. Dan bagaimana dengan kebaikan yang selama ini mengalir di rumah kita sejak Muhammad bersama kita?”
Halimah tidak mundur. Ia menjawab pelan tetapi pasti.
Halimah: “Amanat harus kembali kepada pemiliknya. Jika kita mengembalikannya, kita bukan kalah—kita justru menjaga kehormatan. Adapun berkah, tidak bergantung pada kita menahan Muhammad. Allah tidak melupakan orang yang telah menyusuinya.”
Keduanya berunding lama. Pada akhirnya, keputusan jatuh pada satu hal: keselamatan Muhammad lebih utama daripada gengsi. Pagi-pagi sekali mereka bersiap, lalu berangkat ke Makkah bersama Muhammad.
Dalam perjalanan, Muhammad tampak tenang, tetapi matanya menyimpan sesuatu: kerinduan pada padang pasir Bani Sa’ad—teman-temannya, permainan di ruang terbuka, dan hari-hari yang terasa bebas. Namun ia juga menyadari siapa dirinya: seorang anak yatim. Ia mulai paham beban yang dipikul ibunya sejak Abdullah tiada.
Ketika kembali ke Makkah, Muhammad berusaha menghibur Aminah dengan cara anak kecil yang ingin tampak dewasa. Ia duduk dekat ibunya, bercerita tentang kampung, tentang keberanian anak-anak padang pasir, lalu melontarkan janji yang sederhana namun menenangkan.
Muhammad: “Ibu, kelak aku akan menjadi kuat. Aku akan menjaga Ibu… seperti Ayah seharusnya menjaga kita.”
Aminah tersenyum, bukan karena yakin pada gelar dan kedudukan, tetapi karena melihat niat yang tumbuh dalam hati anaknya. Sejak itu Aminah semakin bulat menjadikan Muhammad pusat hidupnya. Ia tidak memikirkan pernikahan lagi, dan orang-orang pun segan melamar—mereka tahu Aminah masih menyimpan duka, dan hidupnya kini sepenuhnya untuk membesarkan putra Abdullah.
Aminah mendidik Muhammad dengan kisah dan nilai. Ia menanamkan kehormatan keluarga, keteguhan hati, dan kemandirian. Ia bercerita tentang Abdullah—keberanian, kisah penebusan, dan kemuliaan yang sempat menjelang namun tak sempat diraih. Ia juga menceritakan Abdul Muththalib—kepemimpinan, wibawa, dan ketegaran memikul beban. Lalu kisah Hasyim dan Qushay: tentang jasa, keberanian, dan kemampuan menyatukan Quraisy menjadi kekuatan.
Muhammad mendengarkan dengan saksama. Dalam hatinya muncul perasaan yang belum berbentuk kalimat: bahwa garis kehormatan itu seperti sungai panjang—dan kelak bermuara padanya. Ia harus menjadi “sambungan” dari sesuatu yang besar.
Namun seiring Muhammad tumbuh, Aminah justru makin sering merasa takut. Ia merasa ajalnya mendekat, seolah waktu memotong hari-hari terlalu cepat. Ia menatap Muhammad lebih lama, seakan-akan menyimpan wajah itu dalam ingatan sebelum dipisahkan lagi.
Di antara banyak pertanyaan Muhammad, satu yang paling sering kembali adalah tentang Yatsrib—tentang makam ayahnya. Rindu itu datang berkali-kali, lalu mengeras menjadi keinginan.
Suatu hari, mata Muhammad basah. Ia tersenyum sedih.
Muhammad: “Aku berharap Ayah masih hidup, Ibu. Aku ingin duduk bersamanya di dekat Ka’bah… seperti para pemimpin.”
Aminah tak sanggup menahan air mata. Namun ia berusaha menjawab bukan sebagai ibu yang larut, melainkan ibu yang membentuk.
Aminah: “Itu semua kehendak Allah, Nak. Engkau tidak sendiri—banyak anak kehilangan ayahnya. Jangan jadikan kehilangan sebagai alasan untuk lemah. Kehormatan sejati tidak diwariskan; ia dibangun dengan tangan dan hati sendiri. Bersabarlah. Kita akan pergi ke Yatsrib. Engkau akan menziarahi makam ayahmu dan menenangkan rindu.”
Malam-malam Aminah kembali dihantui bayangan Abdullah. Rasa bersalah menyusup: jika ia pergi, Muhammad akan benar-benar sendiri. Ia menangis dalam diam, seakan berbicara kepada Abdullah.
Aminah (berbisik): “Apakah engkau memanggilku, wahai Abdullah? Apakah Muhammad harus kehilangan ibu sebagaimana ia kehilangan ayah?”
Seolah menjawab, ada “teguran halus” dalam batinnya—bukan suara yang menakutkan, melainkan kesadaran yang menegakkan.
Suara batin: “Engkau percaya kepada Tuhanmu. Mengapa engkau gentar? Allah yang menjaga, Allah yang mendidik. Tidak semua yang engkau cintai bisa engkau ikat dengan tanganmu.”
Aminah bergulat lama sampai ketakutannya perlahan tunduk. Pada suatu malam, tekad itu memadat seperti batu: ia harus pergi ke Yatsrib, menziarahi makam Abdullah—agar rindu Muhammad tidak menjadi luka yang tak tertutup, dan agar ia sendiri berdamai dengan kehilangan.
Ia memanggil Barakah dengan suara tegas.
Aminah: “Bergegaslah, wahai Barakah. Siapkan bekal. Tekadku sudah bulat: kita akan pergi mengunjungi Abdullah.”
Ziarah ke Makam Sang Ayah
Malam itu Barakah hampir tak bisa menahan kegembiraannya. Ia tidak tidur; mondar-mandir menyiapkan perbekalan, merapikan kain, memastikan air dan makanan cukup, menata barang-barang agar ringan dibawa. Saat fajar bergeser menuju siang, ia bergegas ke kamar Muhammad dan membangunkannya dengan suara yang bergetar oleh semangat.
Barakah: “Bangun, tuan kecilku. Kita akan berangkat. Kita pergi ke Yatsrib.”
Muhammad segera duduk, lalu berlari ke ibunya dengan mata menyala.
Muhammad: “Benarkah, Ibu? Ibu sungguh memutuskan mengunjungi ayahku?”
Aminah memandang putranya lama—pandang yang menyimpan rindu dan luka sekaligus. Ia menjawab dengan lembut, seolah takut suaranya pecah.
Aminah: “Benar, Muhammad. Aku sudah memutuskan, dan aku berserah kepada Allah. Insyaallah besok kita berangkat. Apa ada yang ingin kau bawa dari Makkah, atau ada yang ingin kau pamiti?”
Muhammad seperti tak percaya mendengar kata “berangkat” keluar dari bibir ibunya. Kerinduannya kepada Abdullah meledak menjadi kegembiraan yang penuh hormat. Ia mencium Aminah, lalu berbicara cepat—seolah takut kesempatan itu menghilang.
Muhammad: “Aku akan pamit kepada teman-temanku, memeluk Kakek, lalu bertawaf di Ka‘bah. Aku juga ingin memastikan bekal cukup sampai kita pulang. Kita berangkat dengan siapa, Ibu?”
Aminah: “Dengan kafilah yang menuju Syam. Rombongan itu akan melewati jalur yang sama menuju Yatsrib.”
Ucapannya berhenti di tengah. Aminah memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa ia minta.
Aminah: “Ayahmu dulu pergi bersama kafilah seperti ini… dan kita akan menempuh jalan yang pernah ia tempuh. Kita akan sampai di tempat peristirahatan terakhirnya.”
Tangis Aminah tak lagi dapat ditahan. Muhammad ikut berkaca-kaca, tetapi ia menegakkan punggungnya—sekuat yang bisa dilakukan seorang anak.
Muhammad: “Jangan bersedih, Ibu. Kita tak punya daya di hadapan Allah. Aku akan bersamamu. Kelak, ketika aku besar, Ibu akan menemukan pada diriku apa yang Ibu harapkan dari Ayah. Dari Abdullah, Ibu hanya kehilangan jasadnya; tetapi aku akan menjaga namanya tetap hidup.”
Aminah mengusap air matanya, lalu memanggil Barakah.
Aminah: “Pergilah kepada Ayah—Abdul Muththalib. Sampaikan keputusan kita.”
Abdul Muththalib seakan telah mengira kabar itu akan datang. Begitu Barakah menyampaikan pesan, ia segera bangkit dan melangkah menuju rumah Abdullah, membawa kegelisahan yang ditahan rapat agar tidak meruntuhkan wibawa.
Aminah saat itu duduk termenung. Di sudut-sudut rumah, kenangan berdiri seperti bayang: hari-hari pertama menjadi pengantin, malam perpisahan Abdullah untuk berdagang, berita kematiannya, lalu kelahiran Muhammad yang menambal luka sekaligus membuka luka baru.
Ketika Abdul Muththalib masuk, Aminah menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan agar tampak tegar. Setelah duduk, Abdul Muththalib menatap Aminah lama, lalu bertanya pelan namun berat.
Abdul Muththalib: “Engkau benar-benar akan berangkat, wahai Aminah?”
Aminah menahan getar di dadanya.
Aminah: “Benar, Ayah. Kerinduanku kepada Abdullah sudah tak tertahankan.”
Abdul Muththalib menghela napas, seolah napas itu mengangkat beban yang tak pernah selesai.
Abdul Muththalib: “Dan Muhammad?”
Aminah: “Dia lebih merindu dari siapa pun, Ayah. Hatinyalah yang paling terbakar rindu. Ia ingin melihat makam ayahnya—sekadar berdiri di dekatnya, sekadar menenangkan dadanya.”
Aminah menunduk sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang hampir patah.
Aminah: “Aku tak bisa menundanya lagi. Bayangan Abdullah terus ada di hadapanku, dalam tidur dan jaga. Seolah ia memanggilku untuk datang. Aku hanya bisa berserah pada takdir Allah.”
Belum sempat Aminah menyelesaikan kalimatnya, Muhammad muncul dengan wajah cerah, seperti orang membawa kabar baik.
Muhammad: “Ibu, sempurnakan persiapan. Kafilah akan bergerak pada penghujung malam ini.”
Baru setelah itu Muhammad sadar ada kakeknya di sana. Ia segera menghampiri. Abdul Muththalib memeluknya, menciumi keningnya, lalu bertanya dengan lirih.
Abdul Muththalib: “Engkau juga ikut, Muhammad?”
Muhammad: “Ya, Kakek. Aku akan menemui ayahku, Abdullah. Aku akan sampaikan salam Kakek kepadanya.”
Kalimat itu seperti menekan tombol paling rapuh di dada Abdul Muththalib. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia merengkuh Muhammad lebih erat.
Abdul Muththalib: “Sampaikan salamku. Katakan bahwa aku tak pernah melupakannya. Andai tulang-tulangku masih kuat, aku akan ikut bersama kalian. Tetapi usia telah merenggut tenagaku.”
Ia kemudian menepi—menyembunyikan tangisnya, memaksa diri kembali menjadi pemimpin yang tampak kukuh.
Abdul Muththalib: “Aku akan menyiapkan beberapa bekal tambahan untuk kalian.”
Sejak petang, rumah dipenuhi orang-orang yang datang melepas. Ada yang menitipkan salam untuk kerabat di Yatsrib, ada yang meminta Aminah mencari kabar makam keluarga yang wafat di perjalanan masa lalu, ada pula yang berpesan agar dibawakan kurma Yatsrib yang terkenal manis. Suara-suaranya bercampur: rindu, harap, dan kecemasan yang dipendam.
Ketika malam kian dekat dan waktu keberangkatan hampir tiba, Aminah berjalan pelan di dalam rumah, menatap dinding-dindingnya seperti menatap halaman hidup yang akan ditinggalkan. Tangan Aminah menyentuh gelas, mengusap kambing, lalu berhenti pada titik-titik yang menyimpan cerita: tempat ia pernah berdiri melepas Abdullah, tempat ia pernah menangis menerima berita duka, dan tempat ia pernah tersenyum mendengar kabar kelahiran.
Ia menegakkan diri, memaksa kuat. Bekal diangkat ke punggung unta. Aminah, Muhammad, dan Barakah keluar, menuju Ka‘bah untuk bertawaf, lalu bergerak ke luar kota—ke tempat kafilah berkumpul.
Kegaduhan naik perlahan. Unta-unta meringkik, barang-barang diikat, suara pemimpin kafilah memanggil dan memberi tanda. Mereka menaiki tunggangan. Rombongan bergerak, meninggalkan Makkah menuju Yatsrib—dengan wajah yang memikul duka sekaligus harap.
Hari-hari perjalanan berlalu di bawah panas yang keras. Kadang jalan sempit, kadang lapang. Gerak unta mengguncang tubuh dan pikiran. Di antara para musafir, ada yang menghitung laba niaga, ada yang memikirkan pertemuan dan perpisahan, ada yang memegang pedang dengan mata waspada, dan ada pula yang menelan rindu pada sahabat di Syam.
Aminah lebih sering diam. Dalam diamnya, ia merasa seolah dipanggil menuju tempat yang dulu disinggahi Abdullah. Ia mencoba menafsirkan kegelisahan itu sebagai rasa lelah musafir, tetapi bisik dalam dadanya tidak reda. Ia memeluk Muhammad erat—kecupan-kecupan kecilnya seperti obat yang ia ramu sendiri agar tetap sanggup berjalan.
Barakah, yang peka pada perubahan hati tuannya, berusaha mengalihkan kecemasan dengan mengajak Aminah memandang ciptaan Allah: gunung-gunung, bentang pasir, burung-burung, dan tanda-tanda kehidupan yang tumbuh dari tempat yang tampak gersang.
Ketika malam turun, udara berubah. Angin menjadi sejuk. Bulan naik, bintang bertebaran. Wangi tanaman padang—syih, qaishum, dan ‘arar—terbawa lembut. Bahkan unta-unta tampak lebih ringan melangkah. Muhammad tidur nyenyak di sisi Barakah.
Hingga dari kejauhan tampak kepala-kepala pohon kurma—rapat seperti kubah-kubah gelap yang menandai sebuah tanah hidup.
Pemimpin kafilah berseru keras:
Pemimpin kafilah: “Yatsrib! Kita telah sampai!”
Aminah terjaga, menatap pohon-pohon itu dengan dada bergetar. Ia seolah mencari-cari pohon yang menaungi pembaringan abadi Abdullah. Kafilah berhenti di luar kota, menurunkan perbekalan. Aminah segera masuk ke Yatsrib dan menanyakan kampung Bani Najjar.
Orang-orang menyambut tamu Makkah dengan ramah dan cepat. Aminah dibawa menuju rumah pemuka Bani Najjar. Di sana, Aminah memandang seisi rumah dengan gelisah—seolah menunggu jejak suara Abdullah.
Dalam wajah Aminah, tuan rumah membaca duka yang terlalu lama dipendam. Ia menenangkannya dengan kata-kata yang pelan, tidak menggurui.
Tuan rumah Bani Najjar: “Teguhkan hatimu, wahai putri. Setiap yang hidup akan kembali kepada Allah. Suamimu berpulang dengan mengingatmu. Doanya untukmu adalah warisan yang paling mahal.”
Setelah itu, tuan rumah mengajak Aminah, Muhammad, dan Barakah menuju pekuburan Bani Najjar. Di bawah pohon rindang yang daunnya mengayun pelan, ia menunjuk sebuah makam.
Tuan rumah: “Di sinilah Abdullah dimakamkan, wahai Aminah.”
Tangis Aminah pecah. Ia duduk di hadapan makam itu dan berbicara seperti berbicara kepada orang yang masih hidup—bukan karena ia lupa kematian, melainkan karena rindunya tak punya cara lain untuk tumpah.
Aminah: “Lihatlah, Abdullah… ini Muhammad, anakmu. Ia datang menziarahi ayah yang belum pernah ia lihat. Lihatlah, ia membawa cahaya yang dulu kau tafsirkan sebagai berkah.”
Barakah menangis diam-diam. Tuan rumah menunduk, ikut tersentuh. Muhammad berjalan mengelilingi makam ayahnya, lalu duduk. Ia mengusap tanah itu dengan kedua tangannya, kemudian menyentuh batang pohon yang menaungi—seolah ingin menyimpan tempat itu dalam ingatan tubuhnya.
Ketika air mata mulai reda, tuan rumah mengajak Aminah kembali. Di rumah, Aminah merebahkan diri. Kesedihan datang lagi, lebih sunyi namun lebih dalam. Ia berbisik pada Abdullah—seperti orang yang telah menemukan tujuan perjalanannya, tetapi belum menemukan tenang sepenuhnya.
Pendeta yang Penculik
Langkah para pemuka Yatsrib bergerak cepat, seolah kota itu baru saja menerima kabar besar yang harus segera ditanggapi. Sebagian mata terpaku pada Aminah—kecantikannya mengundang hasrat, dan bisik-bisik tentang kemungkinan meminangnya beredar dari mulut ke mulut.
Di sisi lain, sekelompok pendeta Yahudi memandang Muhammad dengan ketelitian yang mengusik. Tatapan mereka bukan tatapan biasa—lebih seperti orang yang sedang mencocokkan sesuatu yang lama tersimpan dalam ingatan dengan sesuatu yang kini berdiri di depan mata. Mereka saling bertukar pandang, lalu bertanya satu sama lain dengan suara yang ditahan.
Pendeta 1: “Di mana kita pernah melihat isyarat seperti ini?”
Pendeta 2: “Apa yang sebenarnya kita saksikan?”
Seorang pendeta yang lebih tua—disebut orang sebagai pendeta agung—menatap Muhammad lama, lalu berkata perlahan, seakan membaca ulang kalimat-kalimat yang dulu pernah ia hafal.
Pendeta Agung: “Tidakkah kalian melihat? Sifat-sifat anak ini mirip dengan gambaran yang selama ini kita kenal dari Taurat: tampan, berasal dari keturunan yang terhormat, dan darah yang bersih.”
Ia kemudian menyusun silsilah itu sebagai argumen: ibu dari Bani Zuhrah; ayahnya Abdullah; kakeknya Abdul Muththalib, pemuka Makkah. Ia mengucapkannya seperti orang yang sedang mengunci kesimpulan.
Pendeta Agung: “Jika memang akan lahir seorang nabi dari bangsa Arab… mengapa bukan dia?”
Seorang pendeta lain menelan ludah, lalu bertanya hati-hati.
Pendeta 3: “Lalu apa yang tuan kehendaki?”
Pendeta agung mengangkat wajahnya. Suaranya menjadi lebih tegas.
Pendeta Agung: “Kita ambil dia. Kita besarkan di tengah kita. Kita ajarkan agama dan tradisi kita—hingga ia tumbuh hanya mengenal kita. Jika kelak ia menjadi nabi, ia akan berdiri untuk kita; menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi Aus dan Khazraj.”
Beberapa orang terkejut, sebagian tergoda. Namun seorang pendeta muda segera menyela, nada suaranya cemas.
Pendeta 4: “Bagaimana caranya? Anak itu bukan sendirian. Ia dikelilingi keluarga dan kerabat. Dan orang Arab menjaga tamu mereka sampai mati.”
Pendeta agung menjawab seolah semua sudah dihitung.
Pendeta Agung: “Kita culik dia dan sembunyikan di benteng. Anak-anak mudah dialihkan, mudah ditipu. Kita pernah melakukannya pada anak-anak lain; sebagian berakhir menjadi bagian dari rumah-rumah kita dan melupakan asal-usulnya.”
Pendeta lain menggeleng, menolak keyakinan itu mentah-mentah.
Pendeta 5: “Tidak semudah itu, wahai tuan. Anak-anak di Yatsrib sangat melekat padanya. Jika ia hilang, teriakan mereka akan menggelegar. Bani Najjar akan bangkit. Quraisy akan datang. Dan jika pertikaian itu pecah, kita sendiri yang menyalakan api yang membakar kita.”
Pendeta agung diam sejenak—diam yang bukan ragu, melainkan mencari celah. Lalu ia menjawab, menurunkan suaranya, seakan rencana itu semakin gelap.
Pendeta Agung: “Kita ambil dia ketika ia menjauh. Ada saat-saat ia memisahkan diri dari teman-temannya. Anak-anak itu akan pulang menangis, lalu—dengan mudah—kita arahkan mereka kepada cerita yang menutup jejak: ‘Ia diterkam binatang buas saat kalian lengah.’”
Seseorang berbisik, setengah ngeri, setengah terpikat.
Pendeta 6: “Apakah tuan sungguh yakin anak itu akan menjadi nabi?”
Pendeta Agung: “Jika ia memang sosok yang kita duga, maka merebutnya sekarang adalah keuntungan besar. Jangan biarkan kesempatan ini lewat.”
Namun penolakan datang lagi—kali ini dari pendeta yang lebih berhitung.
Pendeta 7: “Ia sudah mendekati enam tahun. Anak seusia itu tidak semudah itu melupakan rumah. Ia tampak cerdas dan matang. Jika suatu hari ia mengingat penculikan ini, ia bisa berbalik menjadi musuh paling keras. Dan Aminah tidak akan meninggalkan Yatsrib bila anaknya hilang. Quraisy akan datang. Aus dan Khazraj mungkin bersatu melawan kita. Kita bisa menggali kubur kita sendiri.”
Perdebatan berlangsung lama. Namun pada akhirnya—didorong oleh ambisi dan rasa takut kehilangan “tanda”—mereka memilih untuk tetap bergerak. Orang-orang tertentu ditunjuk untuk menjalankan misi. Mereka mengawasi Muhammad dari jauh, menunggu satu celah kecil yang cukup untuk menghilangkan seorang anak tanpa suara.
Tetapi rencana yang dibangun dalam gelap sering kali mengundang telinga-telinga yang tajam. Penduduk Yatsrib mulai menangkap keganjilan gerak mereka: tatapan yang terlalu lama, langkah yang terlalu dekat, pertemuan yang terlalu sering.
Ketika kecurigaan itu menguat, sebagian orang mendatangi Aminah dengan napas tergesa. Mereka tidak membawa kepastian, tetapi membawa peringatan yang serius.
Penduduk Yatsrib: “Wahai Aminah, berjaga-jagalah. Kami mengendus niat buruk terhadap putramu. Jangan biarkan Muhammad lepas dari pengawasanmu—sesaat pun.”
Aminah mendengar peringatan itu dengan wajah menegang. Rindu yang membawanya ke Yatsrib tiba-tiba berubah menjadi kewaspadaan. Dan di dalam dadanya, ketakutan lama—ketakutan seorang ibu yang sudah lebih dulu kehilangan suami—bangkit kembali, kali ini menuntut satu hal: jangan sampai kehilangan anak.
Wafat
Aminah teringat hari ketika Halimah al-Sa‘diyyah mengembalikan Muhammad ke pangkuannya dengan wajah cemas. Halimah kala itu bercerita tentang orang-orang asing yang pernah berkerumun mengamati Muhammad, seolah sedang menakar kesempatan untuk menculiknya. Kenangan itu kini kembali menyala di Yatsrib, apalagi Aminah juga letih menghadapi lelaki-lelaki yang datang silih berganti memaksanya menikah. Penolakan yang ia ucapkan dengan halus tak lagi membuat mereka berhenti.
Hampir sebulan Aminah tinggal di Yatsrib. Ia belum merasa “selesai” melepas rindu pada Abdullah—seakan tanah yang menutup pusara itu masih meminta ia duduk lebih lama. Namun ia juga melihat kenyataan lain: Muhammad makin dicintai kota itu. Teman-teman kecilnya akan tumbuh menjadi para tokoh, pedagang, dan pemuka masyarakat; persahabatan masa kanak-kanak akan menjadi sandaran kuat bagi perjalanan hidup Muhammad kelak. Pikiran itu sempat membuat Aminah bimbang untuk pulang.
Tetapi kewaspadaan mengalahkan keraguan. Dalam batinnya seolah ada dorongan tegas: cukup; pulanglah sebelum bahaya mendekat. Ia pun memutuskan kembali ke Mekkah.
Kabar keberangkatan Aminah menyentak rumah pemimpin Bani Najjar. Kerabat dan sahabat berdatangan—lelaki dan perempuan—menggenggam perpisahan seperti luka yang baru dibuka. Anak-anak pun menangis, memohon agar Muhammad tetap tinggal.
Anak-anak Yatsrib: “Jangan khawatir, kami semua penjaganya. Muhammad akan aman bersama kami.”
Aminah menahan pedih. Ia menenangkan mereka dengan janji akan kembali berziarah jika Allah memberi kesempatan. Sore itu terasa panjang: penuh pelukan, doa, dan hadiah sederhana—kurma, buah-buahan, bingkisan kecil—yang diberikan bukan karena nilai, melainkan karena cinta.
Di antara para pemberi hadiah, seorang anak seusia Muhammad maju dengan tangan gemetar, menyodorkan patung kecil yang tampak dibuat dari kurma Ajwah.
Anak Yatsrib: “Ambillah, Muhammad. Ini hadiah yang paling kami sayangi.”
Muhammad: “Apa ini, saudaraku?”
Anak Yatsrib: “Tuhan kecil yang akan menjagamu selama perjalanan.”
Muhammad memandang patung itu sejenak, lalu tersenyum—bukan mengejek, melainkan mengerti kepolosan teman kecilnya.
Muhammad: “Biarkan ia tetap bersamamu. Matahari di jalan amat panas—ia bisa meleleh. Dan ia tak sanggup menjaga dirinya sendiri. Makanlah saja, agar kurmanya tidak terbuang.”
Anak itu menangis makin deras, seakan baru paham bahwa perpisahan tak bisa ditawar. Aminah mendekap si anak, menenangkan dengan suara lembut.
Aminah: “Jangan takut, nak. Kami berjalan dalam perlindungan Allah, Tuhan langit dan bumi—yang hidup dan tidak pernah lenyap.”
Keesokan paginya, sebelum kafilah bergerak, Aminah, Muhammad, dan Barakah kembali ke pusara Abdullah. Aminah duduk lama, mengusap tanah dengan tangan yang basah oleh air mata. Muhammad berdiri dekat pusara ayahnya, mengusap tanah itu dengan telapak mungilnya—seolah ingin menyimpan bentuknya di ingatan. Barakah ikut terisak, menahan tubuhnya agar tetap tegak.
Saat panggilan berangkat terdengar, Aminah memanggil keduanya dengan suara pecah.
Aminah: “Mari, Muhammad. Mari, Barakah. Sudah waktunya kita pulang.”
Sebelum beranjak, Aminah menoleh sekali lagi ke pusara Abdullah.
Aminah: “Sampai jumpa, Abdullah. Kami datang karena rindu, dan pulang karena harus. Aku menitipkanmu kepada Allah. Entah aku kembali atau tidak—tetapi hatiku mengatakan pertemuan kita belum selesai.”
Mereka kembali ke rumah pemimpin Bani Najjar, lalu menuju tempat berkumpulnya kafilah. Doa mengiringi langkah mereka.
Penduduk Yatsrib: “Ingatlah kami, wahai Aminah. Jangan lupakan kami.”
Aminah naik unta bersama Muhammad. Barakah mengurus perbekalan di unta lain. Kafilah bergerak meninggalkan Yatsrib hingga kota itu perlahan tenggelam dari pandangan.
Perjalanan menempuh dua marhalah. Mereka tiba di tempat bernama al-Abwa’. Saat itu panas mencapai puncaknya; angin menyapu debu dengan hawa yang membakar. Di tengah cuaca yang mengganas, Aminah mendadak merasakan nyeri menembus dada—sesak yang tak biasa. Ia menoleh pada Barakah dengan mata sayu.
Aminah: “Ini perjalanan yang panjang, wahai Barakah…”
Barakah menyangka itu hanya keluhan musafir.
Barakah: “Kita baru menempuh dua marhalah, tuan putriku. Insyaallah kita akan sampai dengan selamat.”
Aminah menggeleng pelan, seakan maksudnya bukan jarak, melainkan takdir.
Aminah: “Bukan itu… perjalanan panjang yang tiada ujungnya.”
Muhammad melihat ibunya melemah. Ia panik, menyeka wajah Aminah dengan air dari geriba, menggenggam tangan ibunya dan memanggil-manggil.
Muhammad: “Ibu… buka matamu. Lihat aku. Bicaralah padaku.”
Kafilah berhenti. Para tabib berusaha menolong, tetapi wajah-wajah mereka akhirnya menunduk—tak mampu menahan keputusan yang sudah ditetapkan langit. Aminah sempat membuka mata, mencari Muhammad dan Barakah, seolah ingin menunaikan amanat terakhir.
Aminah (kepada Barakah): “Muhammad… jagalah dia. Aku menitipkannya kepadamu.”
Lalu ia menoleh pada putranya, suaranya sangat lirih, tetapi tegas.
Aminah (kepada Muhammad): “Aku titipkan engkau kepada Allah, Nak. Dia yang akan menjaga dan menuntunmu—dengan kasih sayang yang melampaui kasih sayang ibu dan ayah.”
Aminah kembali menatap Barakah, napasnya kian pendek.
Aminah: “Bawalah dia pulang ke Mekkah. Serahkan kepada kakeknya, Abdul Muththalib. Jangan lengah—ada orang-orang yang pernah mengintainya.”
Kemudian Aminah memandang Muhammad untuk terakhir kali.
Aminah: “Semoga Allah memberkahimu sejak kecil wahai putra seorang yang selamat dari kematian karena anugerah sang Maha Kuasa, maha memberi nikmat. Lalu dia ditebus dengan 100 ekor unta dengan undian. Jika apa yang aku lihat dalam tidurku benar, niscaya kau akan menjadi utusan Allah Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung. Engkau akan diutus di tanah halal dan tanah haram, engkau diutus dengan menyatakan kebenaran dan membawa agama, agama ayahmu (Ibrahim), engkau diutus membawa agama yang mudah yaitu agama Islam. Allah akan melarangmu dan melarang kaummu untuk menyembah berhala.”
Nabi mendengarkannya dengan seksama meskipun jiwa kecilnya tengah lara melihat kenyataan yang sedang diderita ibundanya, meskipun apa yang diucapkan ibunya belum sepenuhnya difahami beliau.
“Jangan lupakan ibumu yang berbaring di padang pasir… dan ayahmu yang terbaring di Yatsrib. Jika kelak engkau pergi dan pulang dalam urusan besar, berhentilah sejenak—doakan kami.”
Kata-katanya berhenti. Bibir itu terkatup. Muhammad menjerit memanggil ibunya; Barakah meratap keras. Tangis kafilah pecah, bukan semata karena kematian, tetapi karena seorang anak kini menjadi yatim piatu di hadapan mata mereka.
Aminah dimakamkan di al-Abwa’. Setelah tanah diratakan, kafilah kembali bergerak menuju Mekkah dalam diam yang berat. Barakah memeluk Muhammad erat-erat di atas tunggangan, menahan tangis yang tak habis-habis, sementara gurun membentang luas—seolah ikut menyaksikan perpisahan yang tak bisa diulang.